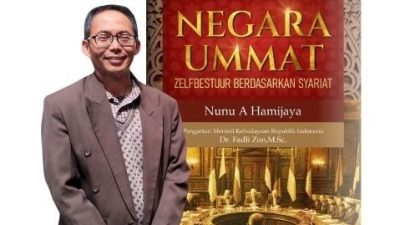CHAIRIL ANWAR masih muda ketika menerima fakta mengerikan, kematian dari orang yang dicintainya–lihat sajak ”Nisan”, sebuah sajak pendek yang diilhami oleh kematian neneknya. Ketika itu–bandingkan dengan perlawanan serta penolaknya pada fakta eksistensial keterbatasan dan kefanaan manusia, yang diungkapkan di dalam diksi ”ingin hidup seribu tahun lagi …”, pada sajak ”Aku”–, ia melihat nenek tercintanya meninggal dunia, dan menemukan dua fakta. Bahwa (1) manusia itu pasti mati, bahwa si kehidupan serta kesempatan buat mengeksiskan keberadaan dan kemerdekaan berada (hidup) di dunia itu ternyata dibatasi takdir (pasti) mati–serta di latar belakang, pengaturan Yang Kuasa, yang seperti bersengaja merahasiakan entah kapan tibanya kematian itu bagi si bersangkutan, sehingga terkadang seperti khianat dengan bersipat improvisatif datang sekonyong-konyong.
Dan (2) kematian yang entah kapan tibanya itu semacam pengkhianatan bagi kebebasan ada dan mengada dalam (kesempatan) hidup, tapi tragika improvisatif itu terkadang tak dianggap penyiksaan dan pengakhiran tragis dari keberadaan merdeka, bahkan justru–untuk si bersangkutan–, membuat semacam kesadaan kefanaan dari suatu keberadaan, sehingga hal mati yang mendadak itu malahan dinantikan, dan sekaligus diterima dengan keikhlasan. Malah tidak diterima sebagai sesuatu yang menyakitkan, karena tak bisa ditolak, tapi justru jadi pintu dan jalan buat kembali ada bersama-Nya. Dan dalam sajak pendek itu, ”Nisan”, Chairil Anwar mengkristalkan semua pemikiran itu dengan semacam keheranan, mengapa neneknya sangat siap mati serta sama sekali tak mempersoalkan fakta telah dengan sengaja jadi yang kehilangan dunia–kesempatan berada di dunia dengan mutlak berhak menguasai dunia dan menjadi apa saja.
***
Sekaligus hal itu menerangkan, kenapa Chairil Anwar lebih memilih menjadi orang yang mempertanyakan kematian, kesedihan dari pihak keluarga (oleh) kematian yang tercinta, dan ketidakrelaan mati–setidaknya bila dikaitkan dengan diksi terkenal ”ingin hidup seribu tahun lagi …” itu–, sekaligus menolak ikhlas dan menerima kematian sebagai pembebasan–, lantas jadi yang ikhlas menerima kematian dan Eksistensi Yang Membuat Kematian, lantas menjadi yang religius, atau si ”pemeluk teguh” bila mengikuti idiomnya. Di titik itu ia memilih sikap di seberang, jadi indivu yang lebih senang mempertanyakan semua itu, dan melulu (hidup) terombang-ambing dengan sikap menolak kematian dan pengaturan nasib atau hidup, dengan mmilih tetap sebagai yang merdeka dalam kehidupan, dengan–tidak seperti neneknya–tak ikhlas menerima kematian, takdir diri, dan Eksistensi Prima yang mengadakan dan (bahkan) mengakhiri eksistensi hidup dan dunia.
Keyakinan yang aneh dan (bahkan) orsinil, meski semua menjadi bersipat personal—individual dan bukan universal semesta ilahiah. Lihat, misalnya, sajak duniawi, yang mempertanyakan surga, yang nyaris sejajar dengan fakta kehadiran diksi yang memuja perempuan kongkrit dagingiah dan nakal, yang sangat dikenalnya, sehingga itu amat jauh dibandingkan janji-Nya tentang keberadaan bidadari di surga–yang bukan Tuti, dan sebagainya. Lalu bandingkan pemberontakn itu dengan keikhlasannya yang mengharukan ketika maut itu tak bisa ditolaknya dan mutlak hanya harus diterima–dengan diksi yang tegas menyebutkan keberadaannya itu mutlak hanya di wilayah pemakaan di Jakarta (cq pemakamana Karet), misalnya. Di titik itu, pada akhirnya, ia tidak bisa menolak kematian dan perlahan meletakkan pilihan liar tak natural sebagai si ciptaan, mengendapkan keinginannya buat terus hidup, dengan menerima fakta, bahwa setelah ini hanya ada penguburan dan pemakaman sebagai wilayah sejati buat mengada.
Suatu pengakuan tentang eksistensi sejati. Sekaligus ia menolak seluruh asumsi tentang hidup, tentang aktualisasi potensi (diri) menjadi apa saja selama masih punya keinginan. Ia, mendadak, belajar ikhlas, berendah hati–mungkin: ia mengaku kalah– menerima Eksistensi Prima, serta sekaligus mencoba besiselaras mengikuti kemauan-Nya–dengan beragama, meski tidak disebutkan dalam sajak-sajaknya, tapi kesicenderungan reigius itu terlihat dalam beberapa sajaknya.
***
Saya tak tahu apa lagi yang akan ditulis Chairil Anwar, setelah hal itu disadarinya. Setelah kritis eksistensial tuntas, setelah sadar kalau prinsip mengada serta hidup merdeka dengan menjadikan ego sebagai tuan dari diri sendiri itu keliru, dan memilih jadi ciptaan yang mengakui kekuasaan dari Sang Pencipta, bahwa diri terlahir dengan takdir diri dan harus hidup selaras dengan anjuran agama-Nya–sehingga tabah menghadapi cobaan-derita-godaan. Seharusnya ia (mungkin) akan jadi total religius–pribadi yang lain, yang sangat ketat beragama, sang pemeluk teguh dan bukan si ”binatang jalang yang (sengaja) terbuang dari kumpulannya”. Mungkin–dan hal itu mungkin akan menarik, sebab kita akan mendapatkan sosok Chairil Anwar yang hidup dengan asumsi lain–setidaknya dalam sajak yang kemudian ditulisnya. Pribadi yang bertentangan, meski itu pasti dianggap satu kemandulan dari laku kreasi individuaistik, dengan bersengaja menjadikan dirinya bagian dari eksemplar (orang) yang beriman serta beraga-ma, si yang hidup mengikuti anjuran agama. Mungkin.
Tapi itu bermakna, khazanah sastra Indonesia kehilangan sosok penyair (individualistik) Chairil Anwar–dengan sajak-sajak yang sangat bohemian serta advonturir. Memang. Jadi ada untungnya ia meninggal muda, sehingga ia selalu tampak lebih sebagai si pemberontak, dengan sajak-sajak yang menampakkan diri sebagai sesosok sangat individualstik dan bohemian–si yang semau gue, bukan penganut teguh yang religius, yang bisa mengatasi cobaan serta godaan individual dengan petunjuk agama, kitab suci dan Allah sebagai sumber dan muara mengada. Sakaligus saya merasa beruntung karena bisa menangkap gejolak perlawanan—lebih tepat diskursus, meski hasil akhirnya tak pernah diungkapkan–yang orisninil pada fakta mati, pada takdir kematian yang ditentangnya dari fakta neneknya ikhlas menerima kematian, yang malahan tidak mau melakukan protes pada pengakhiran sewenang-wenang atas potensi hidup, yang dirasakannya tak adil dan melukai perasaan.
Dan sekaligus, saya berharap, ia menemukan itu, di titik menjelang kematiannya–menemukan momen damai bersama Allah dan (setidaknya) di dalam kematiannya, sebab kalau tanpa itu, tanpa keberadaan (pengakuan akan) Allah dan agama, maka itu bemakna vitalisme cuma berubah menjadi Fatalisme. Atau sia-sia saja penjelajahan orsinilnya itu. Memang–tapi di titik itulah makna tragika hidup Chairil Anwar. ***
Beni Setia, Pengarang.