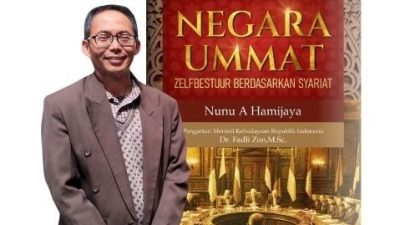SELAMA tiga bulan, terhitung sejak Maret hingga Juni 2025, saya menimba pengalaman di SMKS Muhammadiyah Campaka, sebuah sekolah kejuruan swasta di Purwakarta. Sekolah ini berdiri sebagai kawah candradimuka bagi para calon tenaga kerja terampil di bidang teknik dan teknologi. Terletak di jalur yang strategis, sekolah ini setiap harinya berupaya menjawab tantangan industri dengan mencetak lulusan dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Permesinan (TPM), hingga Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Di sini, di tengah semangat pendidikan vokasi yang kental dengan nilai-nilai keislaman, perjalanan saya sebagai calon guru dimulai.
Ada jurang pemisah antara membayangkan diri menjadi guru dan benar-benar berdiri di depan tiga puluh pasang mata di dalam kelas. Saya datang ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan bekal setumpuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ideal dan teori-teori pedagogi modern dari kampus. Saya pikir, saya sudah siap. Namun, realitas kelas adalah guru terbaik, sekaligus kritikus paling brutal.
Salah satu pukulan telak pertama datang saat saya mengajar IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial). Di atas kertas, rencana saya sempurna: mengajarkan konsep “pencemaran lingkungan” dengan studi kasus dan diskusi. Hasilnya? Tatapan kosong, siswa yang gelisah, dan satu keresahan pamungkas yang belum terjawab : “Apa hubungannya ini dengan jurusan saya, Pak?”
Saat itu saya gagal total. Saya menyajikan materi yang sama rata untuk siswa dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Permesinan (TPM), hingga Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Saya lupa bahwa saya tidak sedang mengajar di SMA; saya berada di jantung pendidikan vokasi yang menuntut relevansi di atas segalanya.
Baru setelah kelas yang canggung itu berakhir, dalam keheningan ruang guru, saya merenung. Seharusnya, saya membawa materi itu ke ‘rumah’ mereka. Seharusnya saya mengajak anak TKR dan TPM turun ke bengkel, mengidentifikasi tumpahan oli dan asap knalpot sebagai bentuk pencemaran nyata. Seharusnya saya menantang anak RPL untuk tidak hanya berdiskusi, tapi merancang prototipe aplikasi pendeteksi polusi. Kegagalan itu mengajarkan saya pelajaran paling fundamental: di SMK, konteks adalah raja. Teori tanpa relevansi hanyalah kebisingan.
Krisis tidak hanya datang dari materi. Ia hadir setiap hari dalam bentuk yang lebih subtil. Saya ingat betul suasana kelas di jam pelajaran terakhir hari Jumat. Saya sedang mencoba menjelaskan cara kerja PLTA dan asal-usul waduk/bendungan, tapi suara saya seolah lenyap ditelan dengungan kipas angin. Di barisan ketiga, cahaya dari layar ponsel lebih menarik perhatian siswa daripada papan tulis. Tiba-tiba, satu celetukan polos terdengar dari pojok ruangan, ‘Pak, kapan pulang?’ Pertanyaan itu, meski jujur, terasa seperti tamparan. Pesaing saya di kelas ini bukanlah rasa kantuk, melainkan algoritma dan penantian bel pulang.
Pertarungan melawan penggunaan gawai yang berlebihan, menjaga atensi siswa yang naik-turun, dan membangkitkan motivasi di jam-jam rawan adalah perang gerilya harian yang tidak pernah ada di buku teks perkuliahan.
Di tengah frustasi itu, secercah harapan datang dari metode yang mengubah total peran mereka: pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning). Keajaibannya bukan pada tugasnya yang keren. Keajaibannya ada pada pergeseran status dari ‘penerima pasif’ materi menjadi ‘pemilik karya’. Kebanggaan saat program aplikasi toko buku mereka berjalan tanpa error untuk pertama kalinya, atau saat database yang mereka rancang berhasil menyimpan data, adalah motivasi intrinsik yang tidak akan pernah bisa saya ciptakan lewat ceramah dua jam. Mereka tidak lagi mengerjakan tugas untuk saya; mereka membangun sesuatu untuk diri mereka sendiri.
Saya melihatnya pada Rara (bukan nama sebenarnya), siswa yang cemerlang dan bersemangat belajar tinggi. Di proyek PBO (Pemrograman Berorientasi Objek), dialah yang paling sering bertanya dan menunjukkan layar komputernya dengan gusar, ‘Pak, ini kenapa logikanya salah terus?’ Untuk pertama kalinya, semangatnya belajar memantik pula semangat saya mengajar. Dia tidak hanya ingin tahu ‘apa’, tapi ‘kenapa’—tidak sekadar mencari nilai, tapi mencari solusi. Itulah kemenangan-kemenangan kecil yang membuat saya bertahan.
Semua dinamika dan pembelajaran berharga ini tentu tidak terjadi di ruang hampa. Saya merasa beruntung mendapatkan kesempatan belajar di SMKS Muhammadiyah Campaka. Di balik tantangan yang ada, saya menemukan lingkungan yang suportif dan terbuka. Sekolah yang dipimpin oleh para pendidik berdedikasi ini tidak hanya fokus pada penyiapan tenaga ahli di bidang teknik dan rekayasa perangkat lunak, tetapi juga konsisten menanamkan nilai-nilai karakter, seperti yang saya saksikan langsung melalui program Smart-Tren Ramadan. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba, bahkan untuk gagal dan belajar dari kesalahan, adalah bukti bahwa sekolah ini merupakan lahan subur untuk bertumbuh, tidak hanya bagi siswanya, tetapi juga bagi kami, para calon guru.
Pada akhirnya, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa menjadi guru bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketahanan. Laporan PPL mungkin akan terbaca sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang terstruktur dan berhasil. Namun di baliknya, ada cerita tentang rencana yang gagal, kelas yang sunyi karena materi yang tidak menarik, dan frustasi menghadapi kedisiplinan siswa. PPL bukanlah panggung pembuktian bahwa kita siap menjadi guru. Sebaliknya, ia adalah cermin yang menunjukkan dengan jelas betapa banyak hal yang masih harus kita pelajari.
Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar SMKS Muhammadiyah Campaka—Bapak Kepala Sekolah, para guru, staf, dan tentu saja, para siswa yang telah menjadi guru terbaik saya dalam perjalanan ini. Semoga niat baik untuk berbagi cerita ini dapat diterima dan membawa manfaat. ***
Mardani Mastiar, mahasiswa PSTI, Praktikan PPL di SMKS Muhammadiyah Campaka, Purwakarta.