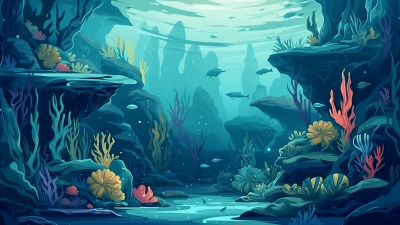SAMPAI hari ini, walaupun sudah banyak perubahan, seringkali aku merasa beraktivitas dari satu target ke target berikutnya. Seperti mengejar waktu dan atau atau dikejar waktu. Seolah-olah setiap detik dibayang-bayangi target yang menanti, mendorongku untuk segera menyelesaikan satu pekerjaan dan mulai pekerjaan yang lain. Melompat dari satu tugas ke tugas berikutnya. Namun, sekarang aku menyadari bahwa ini sebuah kelemahan. Kecenderungan untuk bekerja terburu-buru, seolah dikejar waktu. Meninggalkan apa yang sedang kukerjakan saat ini demi mengejar ide atau pekerjaan lain yang terasa lebih mendesak. Dan hasilnya, pekerjaan terasa setengah hati, tidak tuntas, dan mungkin hasilnya akan lebih baik andai lebih tenang, menikmati, dan tidak tergesa.
Sering ketika sedang asyik membaca sebuah buku, pikiran sudah melayang ke buku lain. Atau saat menulis sebuah paragraf, tiba-tiba ide lain muncul, mendesak untuk segera dituangkan, seolah-olah akan lenyap jika tidak segera direalisasikan. Aku sering terjebak dalam pusaran ini—lompatan dari satu hal ke hal lain, meninggalkan jejak aktivitas yang belum rampung. Bukan karena kurang semangat, tetapi justru karena semangat yang terlalu meluap, ingin merengkuh semua sekaligus. Dan tidak mampu mengendalikan diri.
Di situlah letak jebakannya. Ketergesaan ini membuatku kehilangan kehadiran dalam momen saat ini. Apa yang kukerjakan menjadi sebatas formalitas, bukan karya yang lahir dari fokus dan perhatian penuh. Padahal, jika sedikit lebih tenang, lebih hadir, hasilnya pasti lebih baik, lebih utuh.
Kini, dalam kesenggangan waktu seorang pensiunan, aku belajar untuk mengubah cara hidup dalam endapan waktu. Bahwa bukan lagi sebagai musuh yang harus dikejar, tetapi sebagai sahabat yang meminta untuk hadir sepenuhnya.
Beberapa langkah sederhana untuk mengelola waktu dengan lebih bijak, nyaman dan tidak terburu-buru. Ketika membaca buku, berkomitmen untuk menikmati setiap halaman sebelum melirik buku lain. Saat menulis, membiarkan satu ide mengalir hingga selesai sebelum menyambut ide baru. Bukan tentang menekan kreativitas, tetapi tentang memberi ruang bagi setiap tugas untuk bernapas dan berkembang optimal sebatas kemampuan.
Begitupun ketika melakukan kerja lainnya. Saat olah raga pagi, tidak perlu merasa ditunggu kerjaan di kebun. Ketika di masjid waktunya fokus pada ibadah bukan memikirkan makan malam. Dan sebagainya.
Ide-ide yang muncul di tengah pekerjaan kini cukup dicatat di buku atau smarthphone. Seperti menitipkan pesan pada angin—aku tahu ide itu aman, dan bisa kembali padanya nanti tanpa harus meninggalkan apa yang sedang dikerjakan. Sebelum memulai aktivitas, mengambil napas dalam dan membangun komitmen untuk tidak tergesa-gesa. Ritual kecil ini membantu menenangkan pikiran, mengingatkan untuk hadir sepenuhnya dan menikmati momen kini di sini.
Bahwa keindahan dan kualitas sebuah karya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi pada proses penciptaannya. Menulis satu paragraf dengan penuh perhatian jauh lebih berharga daripada menyelesaikan sepuluh halaman dengan hati yang terpecah. Manusia pastilah bukan mesin. Ada batas berapa banyak yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Menerima keterbatasan ini bukan kekalahan, melainkan kebijaksanaan. Memilih untuk melakukan sedikit dengan baik daripada banyak dengan setengah hati.
Mengendalikan diri untuk hadir sepenuhnya dalam setiap aktivitas adalah bentuk kebebasan. Ketenangan memberi ruang bagi kreativitas untuk berkembang, ide menemukan bentuknya, dan hati merasakan kepuasan. Aku tak lagi ingin dikejar waktu, tetapi ingin berjalan bersisian dengannya, menikmati setiap langkah tanpa beban “selanjutnya.”
Inilah perjalanan untuk berdamai dengan waktu sepenuh kesadaran. Belajar untuk tidak terburu-buru, menikmati apa yang ada di depan kita, dan menciptakan karya yang lahir dari hati yang tenang. Karena di dalam ketenangan, menemukan makna sejati dari setiap momen yang dijalani. ***
Suheryana Bae, kolumnis, tinggal di Ciamis Jawa Barat.