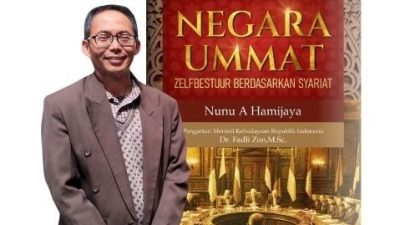Oleh Didin Tulus
PERNAHKAH kita sejenak berhenti dan mendengarkan bisikan angin di antara rimbun dedaunan, atau sekadar merasakan dinginnya air sungai yang mengalir jernih di sela bebatuan? Di sana, ada sebuah irama yang konsisten, sebuah simfoni keseimbangan yang telah dimainkan alam jauh sebelum peradaban mengenal mesin dan beton. Namun, di era di mana kecepatan dianggap sebagai pencapaian utama, kita sering kali lupa bahwa bumi bukanlah warisan yang bisa dihabiskan, melainkan titipan yang menuntut tanggung jawab.
Masyarakat adat Baduy di pedalaman Banten memiliki sebuah kompas hidup yang sangat sakral, sebuah filosofi yang dikenal dengan sebutan Pikukuh. Salah satu lariknya berbunyi: “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak.” Kalimat ini bukan sekadar barisan kata tanpa makna; ia adalah konstitusi batin. Pesan ini menegaskan bahwa gunung tidak boleh dihancurkan dan lembah tidak boleh dirusak. Di mata leluhur Sunda, gunung dan lembah bukanlah objek untuk dikuasai atau dieksploitasi demi angka-angka pertumbuhan ekonomi, melainkan subjek yang harus diajak berdialog dalam harmoni.
Namun, mari kita menilik realitas yang ada sekarang. Pesan luhur itu seolah terbentur tembok keserakahan manusia modern. Kita menyaksikan bagaimana gunung-gunung di berbagai pelosok negeri dikuliti, diambil jantung mineralnya, lalu ditinggalkan dalam keadaan menganga tanpa nyawa. Kita melihat lembah-lembah yang dulunya menjadi penampung air alami, kini dipadati oleh beton-beton angkuh yang menutup pori-pori tanah. Hasilnya? Alam yang kehilangan keseimbangan mulai “berbicara” dengan caranya yang paling pahit.
Banjir bandang yang menerjang pemukiman, tanah longsor yang menelan mimpi-mimpi, hingga krisis air bersih adalah bentuk protes dari bumi yang telah “dilebur” dan “diruksak”. Ketika hutan gundul, ia tidak lagi mampu memeluk air hujan; air itu kemudian berlari liar membawa kehancuran. Kerusakan alam ini adalah cermin retak dari jiwa manusia yang telah kehilangan koneksi dengan akarnya. Kita sering menganggap diri kita sebagai penakluk alam, padahal tanpa alam, manusia hanyalah sebutir debu yang rapuh.
Ajaran Sunda, melalui Pikukuh Baduy, memberikan kita sebuah peta jalan atau penuntun. Hidup selaras dengan bumi berarti memahami batasan. Ada wilayah-wilayah yang bersifat “leuweung titipan” atau hutan titipan yang tidak boleh disentuh oleh nafsu manusia. Konsep ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keuntungan materil jangka pendek: yaitu keberlangsungan napas anak cucu kita di masa depan.
Alam adalah amanah. Sebagaimana kita merawat tubuh sendiri agar tetap sehat, begitulah seharusnya kita memperlakukan bumi. Menjaga keseimbangan alam bukan berarti menolak kemajuan, tetapi memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak mengorbankan fondasi kehidupan kita. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil: menghormati setiap jengkal tanah yang kita pijak, mengurangi jejak karbon, hingga kembali menggaungkan kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan publik.
Pikukuh Baduy adalah pengingat yang abadi. Ia adalah suara sunyi dari masa lalu yang tetap relevan untuk masa depan. Jika kita terus memaksakan diri untuk “melebur” gunung dan “merusak” lembah, maka sejatinya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita kembali pada kesadaran lama yang segar: bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa atasnya. Dengan menjaga gunung agar tetap tegak dan lembah agar tetap asri, kita sebenarnya sedang menjaga napas kita sendiri agar tetap panjang dan harmoni bumi agar tetap terjaga. Sebab, pada akhirnya, bumi akan selalu bisa bertahan tanpa manusia, namun manusia tidak akan pernah bisa bertahan tanpa bumi yang sehat. ***
Didin Tulus, penggiat buku, tinggal di Cimahi.