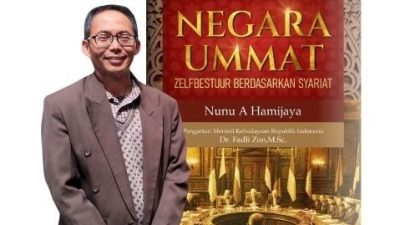Dalam mitologi kuno, keselamatan manusia bergantung pada sebuah bahtera yang memuat keanekaragaman: sepasang dari setiap jenis hewan. Itu adalah simbolisme purba tentang resiliensi, bahwa kelangsungan hidup manusia membutuhkan diversitas alam dengan segala penghuninya. Namun, narasi keselamatan itu kini kita sunting secara brutal. Kita menghadapi ancaman Banjir Sumatera dan krisis ekologi yang kian nyata, namun respons kita justru terjebak dalam teologi bencana yang mematikan nalar.
Hari ini, di bentang alam Sumatera, kita seolah sedang membangun “bahtera” baru. Bedanya, kita tidak lagi memuat keanekaragaman hayati ke dalamnya. Kita melempar hewan-hewan itu ke laut, membakar hutan penyangganya, dan menggantinya dengan muatan baru: monokultur sawit dan hasil keruk mineral.
Ketika banjir bandang menerjang dan menenggelamkan desa-desa, respons kolektif kita sering kali terjebak dalam tagar romantis: #PrayForSumatera, upaya ini adalah senjata paling kuat jika diiringi upaya yang juga hebat. Namun, narasi ini seringkali dijadikan alat legitimiasi ‘saya sudah berbuat‘ dengan harapan semoga “Tuhan tidak Murka”. Namun, mari kita jujur: ini bukan tentang teologi, ini tentang tata ruang. Menyebut bencana hidrometeorologi sebagai “ujian Tuhan” adalah bentuk kemalasan berpikir yang berbahaya. Itu memberikan alibi gratis bagi para perusak lingkungan untuk cuci tangan dari dosa ekologis mereka.
Murka Tuhan dan segala sifat yang dilekatkan padaNya adalah mutlak hak prerogatif Tuhan sebagai Tuhan, sedangkan kita, sebagai manusia wajib bertanggung jawab atas tangan-tangan kita, dan tentunya mendesak mereka yang juga manusia untuk bertanggung jawab atas tangan-tangan mereka.
Banjir Sumatera dan Krisis Ekologi Monokultur
Premisnya sederhana namun mematikan: Dulu kita dijaga oleh jutaan akar dari ribuan spesies pohon yang berbeda — sebuah sistem “spons” alami yang menyerap curah hujan ekstrem. Sekarang, kita menggantinya dengan keseragaman.
Sawit dan bahan tambang adalah komoditas ekonomi yang valid, tetapi dalam skala ekologis, mereka adalah agen penyederhanaan, apalagi pertambangan ilegal. Alam membenci keseragaman. Hutan hujan tropis memiliki arsitektur berlapis yang mampu menahan laju air. Perkebunan monokultur, dengan kanopi seragam dan sistem akar yang dangkal, tidak memiliki kapasitas hidrologis yang sama. Ketika kita mengubah jutaan hektare hutan menjadi “pabrik minyak” terbuka atau lubang tambang, kita secara efektif mencabut sumbatan bak mandi raksasa.
Saat hujan turun, air tidak lagi meresap; ia meluncur. Dan yang ia bawa bukan lagi nutrisi tanah, melainkan lumpur, limbah, dan kematian.
Salah Kaprah “Murka Tuhan”
Ada ironi pahit ketika kita menyalahkan Tuhan atas banjir, sementara tangan kita sendiri yang menandatangani izin konsesi di daerah tangkapan air (catchment area).
Narasi “Tuhan Murka” menempatkan manusia sebagai korban pasif. Padahal, banjir di Sumatera adalah konsekuensi logis dari hukum fisika, bukan metafisika. Jika Anda menggunduli hulu, hilir akan tenggelam. Gravitasi bekerja, terlepas dari seberapa banyak doa yang dipanjatkan.
Menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi kegagalan tata ruang adalah bentuk “gaslighting” spiritual kepada masyarakat. Masyarakat diajak untuk bertobat secara ritual, padahal yang perlu “bertobat” adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kerap kali tunduk pada logika pasar ketimbang logika lingkungan. Argumen klasik yang selalu muncul adalah:
“Kita butuh sawit dan tambang untuk ekonomi.”
Benar, tapi mari bicara tentang opportunity cost. Berapa Rupiah yang dihasilkan dari satu hektare sawit dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat satu kali banjir besar? Hancurnya infrastruktur jalan, jembatan, lumpuhnya pasar, biaya kesehatan pasca-bencana, dan hilangnya produktivitas warga sering kali jauh melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari sektor ekstraktif tersebut.
Kita sedang memprivatisasi keuntungan (ke kantong perusahaan) dan menyosialisasikan kerugian (banjir dinikmati rakyat ramai). Ini adalah model ekonomi bunuh diri. Kita menukar keamanan jangka panjang dengan likuiditas jangka pendek.
Tenggelam Bersama Emas
Jika banjir besar benar-benar datang seperti zaman Nuh, “bahtera” modern yang kita bangun dari sawit dan batubara ini tidak akan mengapung. Ia akan tenggelam karena keberat muatan keserakahan.
Sudah saatnya kita berhenti bersembunyi di balik tagar doa dan mulai menuntut audit lingkungan yang brutal. Tuhan tidak sedang murka; Dia hanya membiarkan hukum alam bekerja terhadap manusia yang lebih mencintai komoditas daripada kehidupan itu sendiri.
Jangan berdoa agar hujan berhenti. Berdoalah agar kita punya keberanian untuk menghentikan gergaji mesin dan menutup lubang tambang ilegal, lalu bekerjalah untuk mewujudkannya.