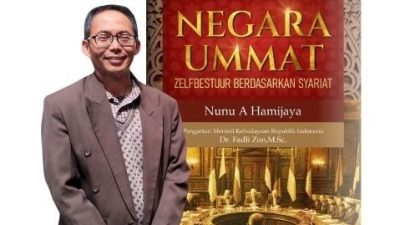Oleh Beni Setia
SEUSAI di-launching di Bandar Lampung, Lampung, 27Agustus 2014, kumpulan puisi dwi-bahasa; (Indonesia dan Inggris) Diro Aritonang, Dendang Krakatau (Song of Krakatoa), di-launching di Bandung–bersama pameran lukisan tentang Krakatau. Saya tak tahu, apa ada peluncuran lain setelah di Bandung ini, karena yang dihadirkan dalam buku itu sebenarnya bukan cuma puisi tentang satu ledakan besar (Krakatau), tapi juga: apa makna dari ledakan besar dari (gunung) Krakatau itu sendiri. Apa akibatnya? Apa kita masih mau mengingatnya? Apa arti bencana besar itu? Kenapa kita harus terus mengingatnya?
Karena, pada dasarnya, 27 Agustus 2014 itu hari peringatan dari erupsi raksasa Krakatau–yang selain dirayakan dengan launching buku itu, juga dengan pembacaan ”Syair Lampung Karam”, catatan biografis dari Muhammad Saleh tentang bencana tsunami di Lampung. Satu catatan sastrawi–diterbitkan di Singapura, ditulis di Singapura selama mengungsi dari trauma bencana Lampung, dan terlupa sebelum bukunya ditemukan terselip di rak filologi Leiden oleh Sayudi Sanuri. Sebuah fakta, bahwa letusan itu ada mengapungkan sekian kubik abu, serta membuat ruang kosong sekian kubik sehingga air laut yang naik dan terserap di lubang itu kembali ke pesisir yang terdekat. Lampung karam–juga Banten–, bahkan sampai ke Afrika, Australia, dan Amerika Selatan.
Itu makna dari peringatan letusan Krakatau 137 tahun lalu–yang sekitar 6 tahun sebelumnya telah diramal oleh Ranggawasita, tentang ihwal bencana si Gunung Kapi, dalam buku klasik Kitab Radja Purwa. Tapi apa Ranggawasita itu sakti? Di luar itu, kenapa jejeran gunung berapi di Indonesia itu–yang terkenal itu supervolcano Toba, kemudian Tambora, meski kita harus mulai menyusuri jejak Gunung Sunda, pencipta kaldera besar Bandung–dilupakan, tak mau tahu kalau letusan yang bersiserentak itu diasumsikan memusnahkan kebudayaan maju Atlantis. Tapi apakah si Atlantis ada di Indonesia? Diro Aritonang tak bercerita tentang itu, tapi sajak panjang ”Tour Gunung di Dunia”, bercerita tentang potensi kemusnahan dunia akibat letusan gunung berapi–dan bagaimana kalau semua gunung berapi itu serentak meletus?.
Dan di imajinasi saya, bola planit Bumi bocor di sana-sini, terbang meliar tanpa garis edar, menubruk si planit lain sebagai akhir keberadaan. Tapi apa itu ada di buku Dendang Krakatau? Tidak ada. Tapi ke arah sana sesungguhnya peringatan 131 tahun
letusan Krakatau, berbentuk puisi, itu dirayakan. Bahwa kita ini hidup di daerah tidak aman, bahwa Atlatis musnah, bahwa letusan Galunggung mengirim debu setebal 4 cm
pada atap rumah-rumah di Bandung Raya, bahwa 138 tahun lalu itu Krakatau meletus, dan sesaat mungkin semua gunung di Indonesia meletus, dan …
***
Soekarno melakukan pidato pembelaan di Pengadilan Bandung, di Gedung Landrat yang kini menjadi Gedung Indonesia Menggugat–gedung kesenian alternatif di Bandung. Pembelaan cemerlang, ihwal makna aktivifas memerdekaan diri dari ulah tangan-tangan imperialis-kolonialisme Belanda–yang kemudian dijadikan buku klasik berjudul Indonesia Menggugat. Gugatan yang lebih keras dari sindiran ironis seorang Ki Hadjar Dewantara via esai ”Als ik een Nederlander was” di De Expres, 19/08/1913 –108 tahun lalu. Tapi Ki Hadjar Dewantara, si kelompok keluarga Sala yang memilih kepriyayian intelektual ketimbang kekuasaan feodal: dihukum. Terlebih Soekarno.
Tapi kita kembali ke ”Gedung Indonesia Menggugat” bukan untuk mengenang Soekarno, romantisme atau tragedi akhir kekuasaan Soekarno–tapi untuk mengenang bahaya di antara Jawa dan Sumatera, di Selat Sunda. Akan ada letusan lagi–tak hanya kepulan asap dan lelehan lava yang membuat tanah kepulauan bertambah luas dengan aneka kehidupan fauna serta flora yang alami–, dan itu seharusnya disadari si banyak pihak. Bahwa Lampung pernah tenggelam dan nyaris tak dihuni orang lagi–sebelum transmigrasi digalakan Belanda. Bahwa Tambora memusnahkan dua kerajaan kecil di lerengnya–atau si Mataram Hindu yang dimusnahkan abu Merapi-, bahwa cekungan Bandung jadi danau gara-gara lava menutup arus Citarum, serta kaldera Bandung itu sebenarnya telah terbentuk oleh letusan purbani. Ingatkah akan itu? Diwaspadaikah?
Tapi siapa peduli. Bukankah banjir di Bandung Selatan hanya terjadi di musim penghujan? Bukankah sampah itu hanya menggunung kalau DKP enggan membayar mahal tukang sampah dan sistim pengangkutan sampah–sehingga si inciniator harus ditolak–? Dan meski tidak menunjuk semua itu disentuh Diro Aritonang–sejak lulus SMA ada di Bandung, telah ber-KTP Bandung, bekerja, serta beristri, anak, serta kini bercucu di Bandung. Lihat sajak ”Di Belakang Rumahku”, yang bercerita tentang data faktual, saksi mata dari letusan Krakatau itu, Maemunah (1867-2012), orang Kalianda yang berlagak tidak tahu apa-apa dan tak ingin mengingat lagi kengerian dari letusan Krakatau–selain suasana saat letusan yang disinggungnya dengan teramat sederhana..
Hampir sebanding dengan sosok si estetikus, yang nyaris bersengaja melupakan sejarah dalam sajak ”Di Hadapan Dua Lukisan Srihadi”–dan itu pasti sebuah bingkai piguratif dengan cakrawala luas yang kosong. Karena itu lahir sajak ”Meraup Corak Warna Kemurkaan Krakatau”, sebagai titik ekstrem dari egoistik mengabadikan sosok Krakatau dalam lukisan–dengan abu vulkanik Krakatau. Meski begitu kita tetap (sejenak) terlena akan/pada ancaman Krakatau—bahkan ancaman dari aneka rangkaian gunung berapi di Indonesia. Mungkin karena tiap ada letusan gunung berapi bermak-na ada proyek pengungsian, rehabilitasi ruang, dan mi instant. Ujung-ujungnya ,,, duit. Sebuah asumsi rutin bernampan profit.
***
Tahun 2022, Kelud–kata orang, itu bermula dari diksi, kelut, sapu, kalau di dalam bahasa Jawa, hingga akan selalu berhamburan debu saat Yang Suci melakukan pembersihan–meletus. Caruban sekitar 50 km di barat, agak ke utara, terdampak tapi tak separah dari Sala dan Yogya, yang sebenarnya lebih jauh–, meski Kediri, Malang, dan Blitar gelagapan. Letusan macam itu pula yang mungkin memusnahkan kejayaan kerajaan kecil kuno di Malang, di sisi timur selatan kaki Kelud. Jadi gunung berapi tidak bisa diramalkan–sehingga Kelud diidentikan dengan raksasa angkara murka tapi sakti, yang atas nama cinta disuruh menggali sumur dan ditimbuni sampai tak bisa ke luar lagi. Tapi ia masih hidup, dan ia sangat marah dikhianati, serta sesumbar mengancam kehidupan di permukaan yang telah mengkhianatinya. Apakah Krakatau punya raksasa yang angkara dan telah mengutuk?
Saya teringat komik rekaan Ganes TH–”Si Buta dari Gua Hantu” yang terkenal itu–, yang bercerita tanah subur yang dimurkai, karena si pemilik sewenang-wenang pada orang kecil itu, yang disengsarakannya dengan terus diminta bekerja dengan dimata-matai kelompok preman bayaran. Apa raksasa ketakadilan itu yang akan bangkit dari Selat Sunda? Saya jauh di timur, di Caruban–Kelud seperti usil melewati kota kami, meski ke barat daya, dalam sebaran berujud kipas: abu mengsihunjam dahsyat. Orang-orang menyembunyikan diri dengan masker, berlagak mau tidur, meski matanya amat nyalang mengintip kesempatan jadi maling–kalau tak salah, ini semua telah disajakkan di dalam salah satu rangkai sajak dalam bukuku, Legiun Asing. Tapi apakah itu penting? Bukankah setiap orang sudah nyalang meski tanpa pakai masker—ber-homo homini lupus–?
Saya tidak tahu, meski sangat sadar: itu awal suatu revolusi mental–meski ingin meniru orang Jepang, yang santun dan tegas menyebutnya restorasi. Apalah arti istilah bila hanya diomongkan dan tidak melakukan apa-apa–sehingga akhirnya gunung ikut berbicara. Barangkali itu yang mau dikatakan oleh Diro Aritonang, setidaknya selepas antoloji puisi Nyanyian Bawah Tanah, yang mengundang kehadiran intel (tentara) di Rumentang Siang (Bandung)–di sekitar dekade 1980-an, di zaman Orba.***
Beni Setia, Pengarang.