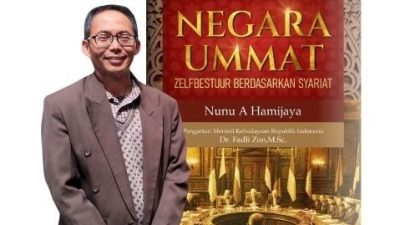DALAM status FB yang diunggahnya pada 11/08.2016, 03:35, Godi Suwarna (GS), menyatakan sudah lama ia membiasakan diri menulis status dalam bahasa Sunda, dan itu menjadi upaya minimalis untuk mengembangkan bahasa ibu, Sunda, dari kuatnya dominasi fragmatis dari (bahasa) Indonesia. Itu bagus, saya pikir—terlebih bagi orang macam penulis, yang terperangkap dalam bahasa Indonesia di tengah arus komunikasi sosial kesekitaran yang berbahasa Jawa. Tapi apakah GS konsisten?
Di status FB yang diunggahnya lebih kemudian—dari status FB yang dikutip di awal, dari FB di sekitar 13 jam sebelum 12/08.2016 06:12—, GS melontarkan sebuah pernyataan, bahwa sebentar lagi akan terbit novel Deng baru, yang, katanya, berasal dari novel tipis Deng di dalam bahasa Sunda—diterjemahkan ke bahasa Indonrsia oleh Deri Hudaya, berilustrasi cover karya Hanafi Muhamad, dengan tata huruf cover oleh Nazarugin Azhar, meski masih menunggu ”kata pengantar” Hawe Setiawan, yang belum selesai. Bagus. Pikirku. Tapi ini agak tidak sportif juga, karena Deng, yang bagi penulis, yang pernah intim berkomunikasi dalam bahasa Sunda itu seperti dipaksa untuk lebih someah dengan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Hal itu—tidak boleh tidak—, mengingatkan saya pada sosok Suparto Broto, almarhum, sastrawan Jawa yang pernah menjelajahi sastra Indonesia, tapi memilih buat lebih inten menulis dalam bahasa Jawa, bersastra dengan berbahasa Jawa. Baik dengan melulu menulis di dalam bahasa Jawa, atau ikut andil membiayai penerbitan (buku) karyanya dalam bahasa Jawa dalam ujud kerja sama dengan penerbit, dengan ikut menanggung (separuh) biaya produksi. Hasil dari penjualan yang separuh (harga) itu kemudian djadikan modal untuk penerbitan lain, sehingga dengan sastra Jawa itu ia tidak mencari penghidupan tapi melulu menghidupi sastra Jawa. Katanya—dalam bahasa Jawa—itu termasuk ngibadah sastra. Persis seperti yang dilakukan Widodo Basuki: menghadiahkan buku karyanya untuk bahan telaah skripsi mahasiswa—yang selalu kesulitan méncari bukunya, selain kerelaan jadi nara sumber.
Bahkan uang ”Hadiah Rancage”, yang bagi beberapa pengarang Jawa dipakai pengganti biaya cetak (buku) sendiri, pernah tidak diambilnya tapi dipakainya untuk menghidupi komunitas persatuan pengarang Jawa (di satu sisi), dan uang hadiah untuk Lomba Menulis Kritik Sastra Jawa. Itu dianggapnya sebagai aplikasi (konsekuen) dari asumsinya, bahwa (sebuah) karya sastra cuma akan abadi kalau berujud buku dan bukan hanya karya di dalam majalah/koran. Sekaligus berani menekankan, betapa vitalnya eksistensi dari sastra, dan terutama bahasa Jawa, di tengah dominasi bahasa Indonesia, sehingga (ia) berani menerakan secuil catatan di buku-bukunya itu, bahwa buku berbahasa Jawa itu tak boleh diterjemahkan (siapapun) ke bahasa Indonesia meskipun dibolehkan dan dibebaskan untuk dterjemahkan ke bahasa lain di luar bahasa Indonesia.
Ada semacam protes kepada kuatnya cengkeraman bahasa Indonesia, yang secara politis diposisikan sebagai bahasa persatuan, sehingga posisi semua bahasa daerah terpinggirkan, meski tetap punya kesempatan hidup sebagai bahasa pegantar dalam pendidikan di tingkat elementer kelas 1-2 SD—tapi bahasa Indonesia itu tidak harus jadi yang diutamakan setelah bahasa Inggris jadi dominan. Setidaknya ketika bahasa Indonesia ingin jadi yang kosmoplitan dan diterima sebagai bagian dari dunia global, dan itu tidak terlalu berhasil meski sukses me-marjinalkan bahasa daerah. Dan di titik ketika bahasa daerah itu seperti diabaikan, dilupakan, serta tidak punya prospek: Suparto Broto memberontak. Ia kini malahan coba mensejajarkan bahasa Jawa dengan bahasa Inggris, dan sebagainya, tidak mau dianggap dan diremehkan sebagai yang subordinan dari bahasa Indonesia.
Jadi tak heran kalau ia bersikukuh menyadur cetita detektif dari buku berbahasa Inggris atau Belanda, jadi karya berbahasa Jawa bergenre detektif—sebagai varian dari crita panglipur wuyung, cerita penghibur lara. Dan penyaduran dan penterjemahan ini mengingatkan saya pada laku Duduh Durachman atau Hawe Setiawan yang mencoba memberi citra internasional kepada bahasa Sunda—dengan menterjemahan karya dunia dalam versi bahasa Sunda. Suparto Broto juga punya cita-cita ajaib, bahwa film seri di TV itu seharusnya di-dub bahasa Daerah—meski tetap diberi teks bahasa Indonesia—, sehingga muncul lelucon ankronisme di JTV, orang kulit putih di-dub Jawa sub Surabaya dan yang kulit hitam diberi aksen dubing Madura. Tapi itu terobosan. Mungkin akan asyik kalau sinetron serta film seri di TV di Jawa Barat diberi dubing basa Sunda.
Memang. Tapi apa mungkin membayangkan GS jadi ekstrem menolak karyanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia—tapi diterjemahkan ke bahasa Inggris, Belanda, dan Jawa, meski beberapa puisi Sundanya pernah tampil dalam teaterisasi dengan lisanan berbahasa Inggris? Dan terasa menyakitkan kalau kita pelan dipaksa membandingkan ungkapan khas GS, yang menggugah dalam bahasa Sunda di dalam ujud baru bahasa Indonesia—yang sangat memperdulikan rasa dari bahasa Sunda dan perasaan manusia Sunda daripada citra rasa bahasa Indonesia dan perasaan manusia Indonesia. Karena itu terjemahan dari sastra Sunda, dalam bahasa Indoneia—setidaknya bagi saya—, terkadang seperti ngageurihan hate, yang ”sakitnya itu di sini”, dibandingkan dengan langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris, atau Jepang. Meski itu masih lebih baik ketimbang tenggelam dalam rawa-rawa etnik, yang sangat lokal. ***
Beni Setia, Pengarang.