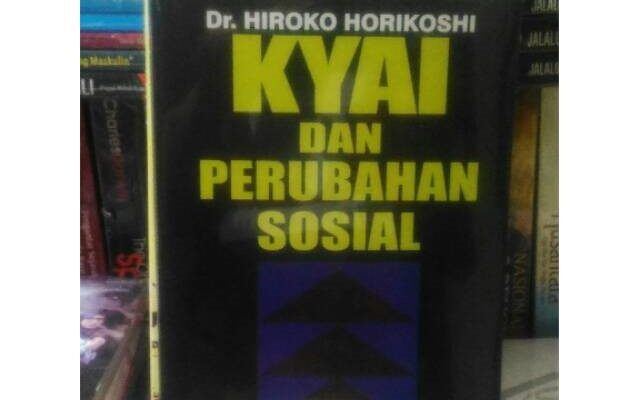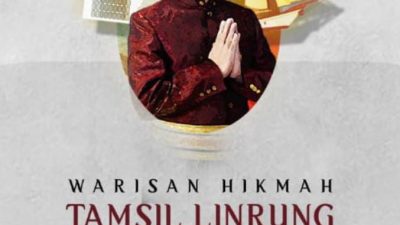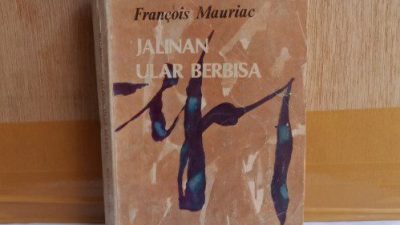Oleh Warsa Suwarsa
A. Sekilas tentang Buku
BUKU karya Hiroko Horikoshi berjudul Kiai dan Perubahan Sosial membahas tentang ajengan (kiai) dan ulama di perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kiai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut.
Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kiai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kiai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain.
Satu sisi Geertz menyebutkan kiai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kiai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[ Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup kiai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.]
Suatu kelompok komunitas ataupun masyarakat memiliki semacam lambang dominan yang berfungsi efektif dalam mempersatukan kelompok dan merupakan pendorong bagi kegiatan anggotanya. Bagi masyarakat Islam di perdesaan, peran ini penting ada, untuk membentengi umat dan cita-cita Islam terhadap ancaman kekuatan sekuler dari luar.
Simbol dominan kiai-kiai di beberapa daerah di Jawa Barat ditandai oleh kekhasan sifat yang ada dalam diri kiai tersebut yaitu kharismatik. Oleh karena itu sifatnya yang sangat karismatik, maka posisi kiai begitu mendapat perhatian di dalam kehidupan masyarakat. Meningalnya seorang kiai yang demikian biasanya menjadi pertanda berakhirnya fenomena kharismatik, dan sedikitnya masyarakat akan kehilangan pemimpin pemersatu dan sekaligus kehilangan kekuatan atau daya bagi kelangsungan hidupnya.
Hasil penelitian Horikoshi ini bisa dibandingkan dengan buku Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup kiai karya Zamakhsarie Dhofier. Zamakhsarie melakukan penelitian terhadap dua pondok pesantren yang ada di Jawa Timur pada tahun 1977-1978. Hasil penelitiannya tersebut jika dibandingkan dengan buku Hirokoshi ada titik temu namun mengandung beberapa perbedaaan karena bedanya lokus penelitian, terjadinya perbedaan sosial-kultural. Di Jawa Timur, terutama Jombang, Zamakhsarie menyimpulkan, kiai tidak hanya menyalin dirinya agar menjadi kharismatik juga harus mengupayakan masyarakat agar memiliki kekuatan yang dihasilkan dari unit pokok kehidupan yaitu keluarga.[Zamakhsarie Dhofier. 1982. Hal 72]
Namun tetap saja, dalam hal pemeliharaan tradisi Islam, di dalam kehidupan masyarakat selalu beralih ke tangan ulama. Seorang ulama adalah pejabat keagamaan. Ia menjabat urusan agama, pada perantara keulamaan Islam, yang secara tradisional telah dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah perdesaan yang kuat yang mengkhususkan diri dalam mencetak kader ulama dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga ortodoksi Islam. Pencetakan kader-kader ulama (kiai) ini disebutkan oleh Zamakhsarie Dhofier sebagai ciri khusus kehidupan sosial di perdesaan, karena betapa pun juga, peran lembaga keagamaan seperti pondok pesantren begitu penting kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hirarki yang jelas dalam lembaga keagamaan ini bukan berarti adanya dominasi dalam kehidupan namun dipengaruhi oleh iklim patriarki abad pertengahan baik dalam tradisi Islam maupun Barat.
Memang ada perbedaan peran dan status antara kiai sebagai tipe kepemimpinan yang simbolik dan ulama yang lebih mengedepankan kepemimpinan adminisratif. Menurut Horikoshi, perbedaan ini hampir belum pernah terjadi dalam solidaritas pondok pesantren secara internal. Perbedaan lahir disebabkan salah satunya oleh menajamnya sebutan terhadap umat Islam sendiri hingga kepada lembaga keislamannya. Antara pesantren tradisional dan modern, Islam tradisional dan Islam modern. Sudah tentu perbedaan ini mengakibatkan lahirnya sentiment-sentimen subyektif, misalnya, sedikit sekali peneliti yang melakukan penelaahan terhadap gerak kehidupan Islam tradisional, akibatnya, pandangan terhadap Islam tradisional mereka dapat dari para penganut Islam modern, dan tentu saja terjadi banyak kesalahan di sana-sini karena mereka menjadi tidak obyektif dalam memberikan pandangan terhadap hal ini. Deliar Noer tidak memberikan rasa simpatik dalam mengulas masalah kiai dan Islam tradisional.
B. Priangan dan Ajengan
Daerah Priangan terbentang sepanjang pantai Tenggara Jawa Barat menghadap Samudera India. Pasundan seperti halnya kerajaan Mataram di Jawa Tengah, kesuburan tanah dan pertanian ini pulalah yang menarik orang-orang Belanda berdatangan ke daerah ini pada masa tiga setengah abad penjajahan sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Proses integrasi sosial budaya masyarakat Priangan ke dalam ekonomi dan sistem nasional di mulai sejak awal tahun 1677 ketika kerajaan Jawa Mataram menyewakan Daerah Pasundan, Jawa Barat, kepada prusahaan Belanda (VOC). Belanda membangun afdelling atau kontrak sebagai basis mereka dalam melebarkan kebijakan Sistem Tanam Paksa di daerah Priangan atau Preangerstelsel. Setiap desa secara kolektif bertanggungjawab untuk menyerahkan sejumlah tertentu kopi dengan penggantian uang tunai yang sangat minim. Sistem tanam paksa ini menyebabkan rakyat desa memikul beban berat untuk mengangkut kopi itu ke Batavia, yang di pihak lain, juga mendukung pendapatan bupati, camat, dan kepala desa.
Agama Islam merupakan elemen paling penting yang memberi bentuk kehidupan mayoritas penduduk daerah itu.
Garut, seperti juga Tasikmalaya, merupakan daerah Islam ortodoks, dan pesantren-pesantren yang terkenal di Jawa Barat terletak di tempat semacam ini, seperti di Leles, Cibatu, Limbangan, dan Malangbong; kedua pesantren yang di sebut terakhir merupakan pendukung pemberontakan Darul Islam (DI/TII). Secara politis, partai Islam di daerah itu juga kuat. Pada pemilihan Umum tahun 1971, perolehan suara antara Golkar dan partai Islam hampir berimbang.
Bagi penduduk daerah itu, afiliasi agama berikut pengalamannya sangat diperhatikan. Kepala Palang Merah setempat dipaksa mengundurkan diri ketika diketahui bahwa ia penganut sekte Islam Ahmadiyah Qodian.
Seorang kiai yang sudah berumur 70 tahun bertempat tinggal persis di seberang pasar, di pinggir jalan besar. Para pendahulunya, oleh Belanda karena terlibat dalam insiden Cimareme affair-Afdeling B. Sepanjang hidupnya, kiai ini juga merupakan pemimpin moral, keagamaan, dan sosial. Sejak Indonesia merdeka, kiai telah keluar dari partai politik baik di tingkat nasional maupun lokal, karena ia melihat adanya kebobrokan partai politik pada masa pemerintah republik muda itu.
C. Pendiri Desa dan Penduduk
Desa Cipari didirikan oleh seorang bernama Zaenal Abidin sekitar pertengahan abad ke delapan belas. Ia juga disebut dengan nama Embah Bungsu, sebab ia adalah anak termuda dari empat anak remaja setempat yang bernama Ayan Permana Prabu Kuncung Putri.
D. Perkawinan, Tempat Tinggal, dan Mobilitas
Keutuhan desa secara terpadu dan pemeliharaan struktur sosialnya dapat bertahan terhadap pengaruh luar manakala penerimaan terhadap calon penghuni desa benar-benar terkontrol dan pengaruh luar terhadap masyarakat dapat dibatasi sekecil mungkin. Berbagai budaya lokal dan faktor ekonomi biasanya membatasi lingkung calon pasangan pengantin, dan karenanya berfungsi melestarikan homogenitas desa. Di kalangan orang Sunda Priangan, bentuk perkawinan yang paling disukai adalah perkawinan antara sepupu, sedangkan pilihan tempat tinggal setelah perkawinan adalah di tempat kediaman pihak perempuan.
E. Perkawinan Endogami
Perkawinan endogami di kalangan kekerabatan yang seketurunan lebih disukai. Penduduk desa menyatakan bahwa mereka lebih menyukai mertua yang sekerabat daripada yang tidak ada hubungan keluarga karena “kemungkinan perbedaan konflik kepentingannya kecil“.
Ada alasan budaya, mengapa yang banyak terjadi adalah perkawinan endogami antarsaudara sepupu, mengapa wanita cenderung menikah dengan saudara sepupu geser sekali yang status generasinya lebih tinggi daripada dengan saudara sepupu yang status generasinya lebih rendah, dan mengapa mereka lebih menyukai paman misan daripada uwa misan. Alasannya ialah untuk menghindari konflik yang timbul akibat perbedaan status kekerabatan dan status saudara karena perkawinan di antara mertua dan menantu berkenaan dengan pilihan tempat tinggal di pihak perempuan.
F. Pranata Keulamaan
Sepanjang sejarah teradisi Islam, ulama telah mengabdi sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas proses penyebaran ortodoksi Islam terhadap generasi Islam selanjutnya. Mereka menguasai pendidikan di madrasah, memegang kekuasaan tertinggi dalam penafsiran Al-Qur’an dan hadist, dan sering pula muncul sebagai pemimpin sosial politik. Umumnya ulama setempat telah dianggap sebagai ahli dan petugas agama dan lembaga masyarakat muslim. Dalam konteks perdesaan Indonesia, tugas ulama bersifat individual, sama sekali bukan bersifat struktural.
Suatu keluarga ulama memiliki dan mengatur lembaga keagamaan dan masyarakat Islam yang dikuasai. Peranan keluarga secara tradisi untuk menghasilkan kader-kader ulama dan memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penduduk. Persaingan selalu dihindri sementara kerja sama dihargai. Persaingan hanya terjadi jika masing-masing ulama berkiprah secara terpisah dari yang lain.
G. Sejarah dan Tradisi
Tradisi dan sejarah juga memberikan pesan kepada tiap generasi baru. Seperangkat kebiasaan keluarga yang berlanjuut, kebanggaan dan tugas-tugas sebagai orang terpilih yang mengabdi pada masalah-masalah Islam, mereka berkata, “Kita harus melanjutkan pekerjaan orang tua.“
Tradisi juga memberikan garis pedoman bagi berfungsinya lembaga ulama serta mempertahankan gairah agama dan partisipasi sosial keluarga dalam masyarakat.
H. Sejarah Awal Keluarga
Secara tradisional, anak termuda selalu mengganti posisi keluarga, sedangkan anak laki-laki yang lebih tua diharapkan keluar dan memantapkan kedudukan mereka yang baru. Keluarga ulama di Cipari masih mempertahankan beberapa keluarga yang masih ada hubungan dengan Tajursena, dan penduduk masyarakat itu masih tetap menghadiri pengajian di Cipari setiap hari Selasa. Di pertengahan akhir abad XIX keturunan Zaenal Abidin berada pada puncak kekuasan mereka. Kekuasaan ini mencapai puncaknya sekitar pergantian abad lalu, yaitu bertepatan dengan periode pembaharuan dalam sejarah Islam. Di tahun 1930-an keluarga ini aktif kembali dalam pergerakan politik Islam yang menentang kekuasaan belanda. Yusuf adalah salah satu dari empat anggota dewan PSII.
I. Sebuah Kesimpulan: Ulama/Kiai sebagai Mediator Masyarakat Perdesaan
Ulama desa atau kiai dikatakan oleh Horikoshi memiliki kedudukan sebagai mediator tradisional, sangat lekat dengan struktur sosial masyarakat desa. Peran dan kedudukannya tersebut tidak hanya berkaitan dengan Islam, juga terhadap aspek kehidupan lainnya. Kiai menempati urutan teratas sebagai sesepuh dalam silsilah keluarga. Dalam perkawinan endogami, hal ini penting sebagai seorang supervisor terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun pada akhirnya, kelompok keluarga inti bisa menjadi pecah disebabkan oleh semakin bertambahnya penduduk dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sosial yang melanda sebuah desa, telah menjadikan peran kiai atau ulama desa menjadi lebih meningkat. Hal ini terjadi karena perubahan atau transisi kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat.
Dapat disimpulkan; kiai atau ulama desa memang memiliki peran penting terhadap perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Entah itu perubahan yang bersifat cepat atau lambat. Meskipun pada dasarnya, kiai atau ulama desa berusaha untuk tetap melestarikan tradisi yang telah dikembangkan oleh leluhurnya, namun tetap saja, proses terjadinya perubahan dari tradisi A ke B begitu besar dipengaruhi oleh adanya mediator tradisional. Sebagai contoh: perubahan yang radikal dalam berkeyakinan sebuah masyarakat, dari penganut animism-hindustik menjadi para penganut Islam tradisional.***
Penulis adalah guru MTs-MA Riyadlul Jannah Cikundul, Sukabumi, Jawa Barat.
Sumber: jabar.nu.or.id