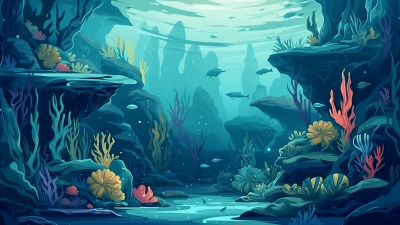Oleh Imam Sahal Ramdhani
KENAPA dr. Aisyah Dahlan “relate” bagi banyak orang?
Pertama, kita harus jujur bahwa konten dr. Aisyah works bagi sebagian keluarga. Inilah fakta sosial tak terbantahkan.
Kenapa bisa begitu? Sebab yang beliau lakukan adalah memaparkan pengalaman empirik, meski kadang bukan riset neuropsikologi murni. Beliau mengambil pola yang sering muncul dalam praktik konseling keluarga, lalu dibungkus dengan bahasa populer agar mudah dicerna awam.
Masalahnya muncul ketika, ada bahasa metaforis (otak reptil, laki-laki fokus ke depan, perempuan multitasking) yang diterima sebagai kebenaran ilmiah literal, lalu dipakai sebagai dasar pola asuh, komunikasi, bahkan pembenaran konflik rumah tangga.
Di sinilah mulai bergeser dari edukasi populer menjadi misleading knowledge.
Di mana Letak Kekeliruannya (secara ilmiah & epistemologis)?
Kekeliruan pertama, adanya Oversimplification, yaitu menyederhanakan sesuatu secara berlebihan sampai maknanya jadi keliru.
Manusia memang memiliki struktur otak yang sama secara evolusioner (brainstem, limbic system, neocortex). Tetapi fungsi psikologis manusia tidak ditentukan satu lapisan otak secara terpisah. Menyebut laki-laki = otak reptil. Sementara perempuan = otak emosional/verbal itu fallacy.
Karena regulasi emosi, empati, bahasa, logika itu merupakan kerja jaringan otak, bukan satu bagian.
Perbedaan individu jauh lebih besar daripada perbedaan jenis kelamin.
Ilmu psikologi modern menyebut ini sebagai within-sex variation > between-sex difference.
Artinya bahwa perbedaan antar-sesama laki-laki bisa lebih ekstrem daripada perbedaan laki-laki vs perempuan.
Kekeliruan kedua, adanya Stereotype Confirmation Loop.
Ketika masyarakat percaya stereotipe, lalu anak laki-laki diasuh dengan ekspektasi “memang susah dinasihati” dan anak perempuan diasuh dengan ekspektasi “harus verbal & emosional”.
Maka yang terjadi bukan pembuktian biologis, tapi melainkan self-fulfilling prophecy.
Contoh sederhananya seseorang percaya bahwa “Aku memang nggak pintar.” Akibatnya ia malas mencoba, cepat menyerah, takut salah.
Kemudian hasilnya, prestasinya benar-benar rendah.
Lalu ia berkata, “Kan benar aku nggak pintar.”
Padahal yang terjadi bukan pembuktian fakta, melainkan pembenaran keyakinan yang keliru.
Kekeliruan ketiga: Authority bias.
Masalahnya bukan beliau dokter atau bukan psikolog. Masalahnya adalah ketika otoritas medis digunakan untuk melegitimasi klaim psikologis yang tidak presisi. Dalam forum ilmiah, metafora = harus dilabeli metafora; popularisasi = tidak boleh mengaburkan konsep. Kalau tidak, publik akan mengira “Oh ini sains. Berarti mutlak.”
Padahal tidak.
Tapi… Apakah semua yang beliau sampaikan salah? Tidak.
Sekarang mari kita lihat dengan adil. Positifnya di mana?
1. Beliau menekankan pentingnya memahami pasangan & anak, ini sejalan dengan prinsip psikologi dan Islam.
2. Beliau ingin orangtua menurunkan ekspektasi ego dengan tidak memaksa pasangan/anak jadi “versi ideal kita”.
3. Bahasanya membumi, ini penting untuk masyarakat awam.
4. Beliau tidak mengajarkan kebencian gender, yang sering disematkan oleh sebagian pengkritik.
Jadi problemnya bukan niat, melainkan kerangka epistemologi.
Terus kenapa kritik dari psikolog & akademisi keras? Soalnya kalau di dunia akademik, ini bukan soal “relate atau tidak” namun apakah konsepnya valid, apakah bisa diterapkan lintas konteks. Apakah berpotensi merusak pola asuh jangka panjang?
Psikolog khawatir karena anak dilabeli sejak kecil, potensi individu dikerdilkan, relasi suami-istri jadi transaksional (“oh dia begitu karena otaknya”.)
Ini kekhawatiran yang sah, bukan kebencian personal.
Lalu, bagaimana posisi Islamic Worldview? Di sinilah kita naik level.
Dalam Islam, manusia tidak direduksi pada biologi. Tidak pula direduksi pada konstruksi sosial semata.
Islam memandang manusia sebagai nafs – ‘aql – qalb – jasad. Laki-laki dan perempuan itu setara dalam taklif; berbeda dalam peran, bukan martabat; dan unik sebagai individu, jadi tak perlu stereotipe. Rasulullah lembut pada anak, mendengarkan istri, tegas saat prinsip, fleksibel dalam metode.
Tidak ada satu pun riwayat Nabi berkata, “Dia begini karena otaknya.”
Yang ada justru “Setiap anak dilahirkan di atas fitrah.” Artinya potensi dibentuk oleh pendidikan, teladan, dan lingkungan dan bukan oleh label biologis sempit.
Boleh menggunakan bahasa populer atau menyederhanakan ilmu. Boleh juga berbagi pengalaman empirik. Tetapi jangan menukar metafora dengan kebenaran dan jangan menukar “yang sering terjadi” dengan “yang pasti terjadi.”
Takutnya yang lahir bukan pencerahan, melainkan keyakinan keliru yang diwariskan.
Dalam Islam, mendidik manusia bukan soal cocok-cocokan metode, namun soal menjaga fitrah, akal, dan adab. ***
Imam Sahal Ramdhani, pengajar Ponpes Sabilunnajat, Dusun Sukamaju, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis/dosen Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis.