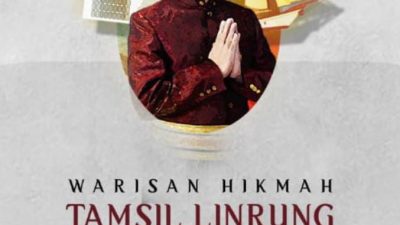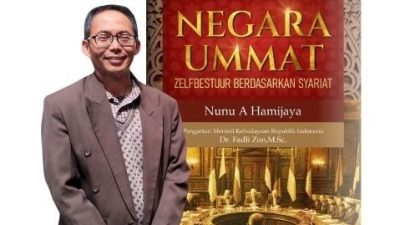Oleh Didin Tulus
ADA aroma khas yang menyambut saya setiap kali melangkah ke Pasar Buku Bekas Palasari di Bandung—campuran debu, kertas tua, dan nostalgia. Tempat ini bukan sekadar pasar, tapi semacam lorong waktu yang membawa saya kembali ke masa-masa ketika buku adalah satu-satunya jendela dunia yang saya miliki.
Hari itu, saya datang dengan niat sederhana: berburu buku dengan bujet Rp100.000. Sebuah tantangan kecil untuk menguji sejauh mana saya bisa menahan godaan di tengah tumpukan literatur yang menggoda. Tapi seperti biasa, Palasari punya cara sendiri untuk membuat saya lupa diri.
Langkah pertama saya bawa ke kios-kios luar, tempat buku-buku ditata seadanya, sebagian bahkan nyaris tak terbaca judulnya karena pudar dimakan waktu. Saya mencari karya Pramoedya Ananta Toer, penulis yang selalu berhasil membuat saya merenung panjang setelah membaca. Sayangnya, yang saya temukan hanyalah replika. Murah memang, tapi bukan yang saya cari. Saya ingin yang asli, yang punya aroma sejarah dan bobot makna.
Saya terus menyusuri lorong-lorong sempit di dalam kompleks Palasari. Di sana, ibu-ibu dan anak-anak sibuk memilih buku pelajaran, sementara saya tetap berharap menemukan “hidden gems” yang bisa membuat hati saya bergetar. Di satu kios, saya menemukan buku Bung Karno cetakan pertama. Mulus, berwibawa, dan mahal. Melebihi bujet saya. Saya hanya bisa menatapnya dengan kagum, lalu melangkah pergi.
Di pemberhentian pertama, saya akhirnya membeli dua buku ringan: Garis Waktu karya Fiersa Besari dan Diary of a Wimpy Kid. Harganya bersahabat, Rp30.000 dan Rp20.000. Sisa bujet saya tinggal Rp50.000, tapi saya tahu petualangan belum selesai.
Godaan berikutnya datang dari kios yang tampak biasa saja, tapi ternyata menyimpan harta karun. Di sana, saya menemukan Saman karya Ayu Utami dan Ateis karya Achdiat K. Mihardja. Dua buku yang sudah lama saya incar. Penjualnya, seorang bapak tua yang ramah, mulai menunjukkan koleksi lainnya: biografi Bung Karno, buku film Indonesia klasik, hingga novel-novel sastra yang jarang saya temui. Saya mulai kalap. Rasanya seperti diracuni oleh semangat literasi yang tak bisa saya tolak.
Saya akhirnya membungkus lima buku dan menghabiskan Rp585.000 di satu kios saja. Total belanja saya hari itu membengkak jadi Rp635.000. Enam kali lipat dari rencana awal. Tapi saya tidak menyesal. Buku-buku itu bukan sekadar barang, mereka adalah investasi jiwa.
Keesokan harinya, saya kembali ke Palasari. Kali ini ke toko Pak Aceng, yang ternyata menyimpan koleksi asli Pram. Saya menemukan Bukan Pasar Malam dan Menggelinding, dua karya yang langka dan berharga. Saya tak bisa menahan diri. Saya beli keduanya dengan harga Rp100.000. Rasanya seperti menemukan harta karun yang selama ini saya cari.
Palasari bukan hanya tentang buku. Ia adalah tentang kenangan, tentang pertemuan dengan orang-orang yang mencintai literasi, tentang obrolan ringan dengan penjual yang tahu isi bukunya lebih dari sekadar harga. Di sana, saya belajar bahwa boros demi buku bukanlah kesalahan. Itu adalah bentuk cinta.
Kini, setiap kali saya membuka lembaran salah satu buku yang saya beli di Palasari, saya seperti kembali ke lorong-lorong sempit itu. Saya ingat suara bapak penjual, tumpukan buku yang nyaris roboh, dan rasa bahagia yang tak bisa dibeli dengan uang. Palasari telah menjadi bagian dari memoar saya—tempat di mana saya menemukan kembali diri saya yang paling jujur: seorang pencinta kata, pemburu makna, dan pemeluk kenangan. ***
Didin Tulus, penggiat buku, tinggal di Cimahi.