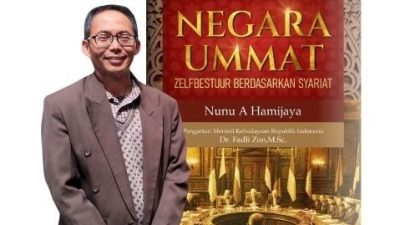KADANG sebuah tulisan—baik dalam berkala semacam koran atau dalam buku—disimpan bukan karena materi tulisannya itu sendiri, tapi lebih sebab niat baik si penulisnya, yang dengan susah payah dan tekun telah menuliskan apa yang dianggapnya penting bagi orang lain, dan bagaimana ia berusaha menyebarkannya sehingga tulisan itu dibaca. Penghormatan ini yang barangkali diabaikan orang yang gemar mencari keunggulan dan keunikan karya itu—lewat kritik. Tapi terkadang saya menyimpan tulisan itu karena ada sesuatu yang penting dan satu kali ingin dibagikan lagi kepada orang lain dan diketahui banyak orang. Menyimpan sebuah tulisan, mengabadikan sebuah buku—dan lalu terlupa dalam rentangan sekian tahun.
****
PERSIS dengan berkala buletin Pawon No 16 tahun ll/2008, dengan teman Pramisme—terutama artikel ”Sudah 2 Tahun, Pram!”, tulisan yang dikutip redaktur dari penjalanjauh.com, dengan menyembunyikan identitas si penulis, dan yang merupakan catatan detik ke detik ketika Pram menjelang meninggal pada 30/4/2006, sekitar jam 9.02. Tulisan itu terlupakan, karena saya mendapatkan buletin itu jauh hari kemudian dari tanggalnya terbit, meski di sampul buletin berwarna merah itu, dengan sosok Pram itu tertulis titi mangsa yang keliru, No 15 Tahun ke-ll. Dari tulisan itu terhadirkan pengalaman seseorang yang melihat proses Pram di dalam sakaratul maut, sejak ia hadir pada Sabtu, jam setengah sepuluh malam sampai ia pulang keesokan paginya [Minggu] dan mendapat sms kematian Pram pada jam sembilan [pagi] lebih.
Ia mencatat, bahwa Pram menangis pada momen itu, meski ia tak menangis untuk hal apapun—bahkan kepulangannya dari pembuangan di Pulau Buru. Kedua, dalam momen itu banyak orang, keluarga dan pelayat—Jo Pakagula, dalam artikel ”Ternyata Pram Lebih Besar dari yang kita Duga”, dalam edisi buletin yang sama, mengatakan bahwa seorang Agus Miftach, intel yang memata-matainya, menyaksikan bahwa Pram sebagai orang yang tak pernah terlihat salat, tapi ia selalu mengingatkan anak-anaknya bila mereka itu terlambat salat–, itu mereka melafalkan bacaan doa, dan yang mungkin tidak bermakna apa-apa baginya, kalau tidak bisa dikatakan malahan menyiksanya. Ketiga, Pram itu berkali-kali mengalami sekarat dan meregang nyawa meski kembali ia [terlihat seperti] bisa mengatasi kematiannya, sehingga semua orang percaya bahwa ia tak akan meninggal—penulis percaya itu, dan karena itu pamit dan meninggalkannya di pagi hari [Minggu] dan karenaya ia tidak bisa melihat momen kematiannnya. [Adik bungsunya, Soesilo, meyakini bahwa Pram itu akan meninggal di dalam usia 100 tahun, dan bukan hanya 81 tahun seperti yang terjadi.]
Meski begitu ia mengkomparasikan banyak momen dari saat Pram menjelang kematian, dengan momen yang diutulis Pram tentang kematian Ayahnya—yang diperlihatkannya di dalam novel Bukan Pasar Malam, dan melihat bagaimana banyak momen itu hampir mirip dan karenanya tulisan itu seperti meramalkan apa yang akan dialaminya—meski saat itu cuma Pram membayangkan dan dengan mendramatisasinya, seperti trauma Susilo tentang kematian Ayahnya setelah sakit dan dibawa pulang dari perawatan di RS, dan karenanya ia ngotot agar Pram tetap di RS dan tidak dibawa pulang ke rumah. Memang! Dan itu menunjukkan bahwa kehebatan Pram bukan saja terletak pada keterkurungan dalam penjara yang membuatnya kreatif, tapi justru imajinasi dan fantasi yang kaya yang membuatnya bisa menulis secara menggigilkan, sekaligus banyaknya pengalaman [pribadi] otentik itu yang membuatnya bisa menghayati liku hidup yang menggigilkan—jadi nyaris mustahil mengarang hanya mengandalkan fantasi dan angan-angan saja. Kita harus mengalami terluka dan setidaknya harus bisa memberi darah dan nyawa pada luka Dan di titik ini, itulah sumbangan terbesar dari tulisan ini—dan itu pula yang membesarkan Pram sebelum ajal menjemputnnya.
Tapi apakah dengan mati ia kalah? Tapi apakah dengan tak mati ia akan terbukti ia tidak terkalahkan, atau—mengutip Budi Darma—hanya jadi bekas sastrawan yang tak lagi bisa menulis karya yang gemilang? Di titik ini, kita tidak bisa berandai-andai—di dalam kesempatan yang sama, dalam tulisan lain, pada edisi Pawon yang sama, seorang Linda Cristanty, yang me-review novel Arus Balik, menunjukkan subyektivitas dari Pram, sehingga sesuatu yang sipatnya lokal [telanjur] dianggap fenomenal.
****
DI luar semua itu, tertinggal satu kebenaran universal, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, dan bagaimana melawan dan menentangnyapun kita tak bisa mengalahkan itu—sebuah janji personal, janji dari kita sebagai manusia dan ciptraan dengan Sang Pencipta–, dan karenanya drama yang dipertontontonkan di dalam tulisan itu membuat kita harus menerima fakta bahwa menerima hidup bermakna berdamai dengan mati, bermakna kita harus mau menerima kematian, dan kalau tidak menerima itu bermakna kita mengingkri janji itu, mengingkari keberadaan si yang memberi hidup [yang kadang hanya dipakai manusia untuk melawan dan mengingkari-Nya], dan karena hidup tak hanya memiliki dimensi sampai di sini saja dan tak berlanjut ke alam sesudah mati, ke fakta adanya Akhirat. Memang! ***
Beni Setia, Pengarang.