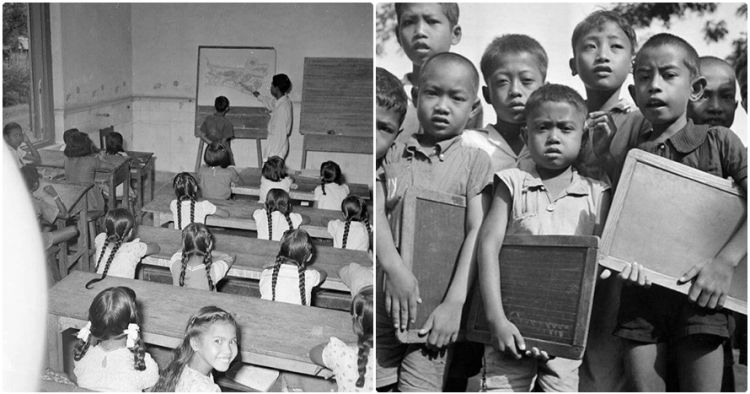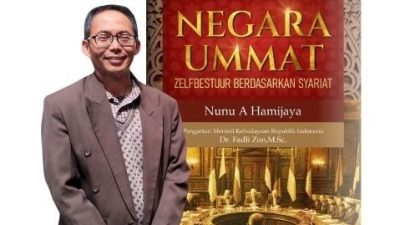Oleh Beni Setia
SAYA baru naik ke kelas VI—atau mungkin masih ke kelas V–, ketika pecah momen pemberontakan G30S. Mungkin tak tepat begitu, maklum usia saya saat itu masih sebelas tahun atau mungkin di awal dua belas tahun, belum mengerti apa-apa—saya tak tahu apa yang terjadi meski banyak rumah anggota PKI dirusak massa di malam hari sehingga hancur, dan bahkan dibakar–, saya tidak tahu apa yang terjadi di malam hari, maklum masyarakat tidak biasa begadang, atau hanya tidur di larut malam, karena tidak terbiasa jaga di malam dengan adanya siaran TV 24. Kehidupan di kampung yang sunyi dan langka hiburan,’
Yang saya ingat: dua hal. Pertama, saat itu sering terjadi arak-arakan, dengan menyertakan iringan drum band, bahkan saling bersaing dan jor-joran untuk tampil lebih jago dan megah dalam menunjukkan kemahiran main musik dan atau sekadar seragam mereka. Kedua, ketika momen pemberontakan itu terjadi—selain bekas kerusakan yang terlihat itu—sekolah [rasanya] baru liburan panjang dan ketika masuk sekolah lagi kelas sering kosong karena ada guru yang pensiun dan pindah, dan tidak segera mendapat ganti—sekaligus ada guru yang dicekal ”tidak boleh” mengajar lagi. Itu momen sekolah bebas, masuk di kelas tapi tak ada pelajaran—kami biasanya menjauhi areal sekolah, di dekat alun-alun, menjauh untuk main bola dan senang karena tak dipangil-panggil untuk masuk—bermain terus sampai suntuk.
Saya ingat itulah saat luang untuk menciptakan permainan kucing-kucingan setahun atau sebulan, dan kadang hanya dua minggu. Biasanya dicari satu kucing utama, lalu semuanya lari dan dikejar yang jadi kucing dan lalu ikut jadi kucing saat ditangkap si kucing utama—ditowel, hingga permainan itu disebut ”kucing towel”. Lantas si kucing baru itu ikut kucing lama untuk menangkap yang lain, yang belum tertangkap—hingga masa bermain bisa melar jadi tidak sejam atau sehari, malah dirancang untuk jadi sebulan atau setahun. Yang menarik—di dekat alun-alun itu ada kantor pos, kantor kecamatan, kantor polisi dan tentara, hingga setiap pagi kami menonton mereka bisa membariskan tahanan untuk dijemur di matahari pagi, karena mereka terlibat pemberontakan itu. Dan saat itu menyebabkan kami disuruh masuk kelas meski sering tidak ada pelajaran dan guru yang mengajar. Dan bersama berita dari RRI, koran atau desas desus, maka yang diuber dan dikepung banyak ”kucing” itu pun segera diberi gelar Syam, Nyoto dan seterusnya—tapi tak berani disebut si Aidit–, meski kadang yang disebut gembong itu segera tertangkap tapi ada anak jagoan dan lihay hingga tak pernah gampang tertangkap dan diberi nama gelaran–yang tak kami pahami siapa—kami hanya menangkap nama dari pemberitaan.
Itu permainan yang lama, diteruskan dan tetap diteruskan selama mungkin—kami menjauhi areal sekolah dan menghidupkan kucing-kucing baru, setengah mengikuti berita tentang upaya menangkap orang-orang yang terlibat pemberontakan. Tapi masa kebebasan bersekolah itu tidak lama, karena kami harus kembali ke kelas dan belajar—ada guru dan ada pelajaran. Tapi rasanya tak terlalu ketat, lebih santai, dan proses pembelajaran tak terlalu diterapkan tegas. Kami masih sering hanya belajar sampai istirahat pertama, dan menjauh untuk main sepak bola dan terutama main ”kucing setahun”—beramai-ramai mengepung si tokoh jagoan yang tertinggal. Ya—sentimentil dan menyenangkan sekali mengenang masa kecil yang indah itu.
Mungkin karena masa sekolah diperpanjang enam bulanan, dan itu jadi berakhir di Juni dan mulai Juli—bukan selalu pas bulan Ramadhan sehingga bisa liburan panjang. Dan mulai saat itu bersekolah jadi santai, selalu harus naik kelas dan lulus seratus persen. Bahkan diusahakan agar terus seratus persen setiap tahun—mungkin karena siswa ikut demo dan jadi demonstran agresif dengan kop KAPPI—gabungan pemuda dan pelajar–, dan sederajat dengan KAMI—ma-hasiswa. Mungkin juga agresivitas itu perlu diredam dengan diberi kemudahan naik kelas dan lulus sekolah, sehingga istilah tinggal kelas tidak lagi dikenal—di kalangan mahasiswa tak naik tingkat adalah biasa, meski terus dihindari kemungkinan DO karena terlalu lama kuliah dan tak lulus-lulusan semesteran.
Kini kita tiba pada periode tak bersekolah (lagi) dan tetap belajar di rumah—tidak di sekolah, demi menghindar dari kemungkinan terjadinya kerumunan—diadakan–, bahkan diharuskan—di TVRI, ada siaran per setengah jam, untuk setiap level pendidikan, untuk membantu suksesnya acara bersekolah di rumah, yang sangat ditunjang oleh teknologi informatika lewat internet dan HP. Bahkan—seperti telah dicanangkan dan akan diselenggarakan tahun ajaran de-pan—disusul dengan peniadaan ujian. Kini, para siswa bisa belajar sendiri, bisa belajar di rumah dengan diawasi orang tua dan dibimbing guru secara daring, dan diharuskan menyelesaikan tu-gas yang diberikan guru, tapi tidak ada ujian. Santai saja—bahkan ada pihak yang minta agar kita berhat-hati, tidak menyamaratakan, karena bahan dan sarana belajar di rumah tidak akan sama antara anak kota dan anak kampung—jangan disamakan.
Saya tak tahu macam apa siswa kita saat nanti—bila tak ada ujian, bahkan nyaris total dianggap bersekolah meski hanya belajar sendiri dan tanpa pengawasan dan penerapan disiplin belajar yang ketat dari guru. Mungkin akan terjadi sukses pembelajaran, dengan angka kenaikan dan lulusan lebih dari seratus persen, maklum telah bertahun-tahun kita berhubungan dengan angka kenaikan dan kelulusan seratus persen—yang dipaksa ada karena guru dan Diknas, bahkan Pemda, takut pada agresif siswa yang sekali waktu pernah ikut demo di era pemberontakan.***
Beni Setia. Pengarang