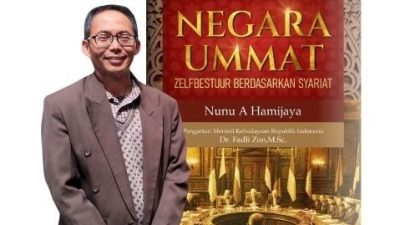MESKI tak mengatakan mustahil dan mentertawakan, Imaniar Yodan Christy, seorang Guru SMP Kristen YSKI di Semarang (lihat, ”15 Menit” , pada rubrik Pendidikan, Basis No 05-06, Tahun ke-69, 2018, hal. 57), menandaskan bahwa pembiasaan Literasi di sekolah itu nonsens. Maksudnya, dengan melatih siswa, di sebelum jam pelajaran dimulai, selama 15 menit membaca buku teks non-pelajaran, dan itu ditandai dengan bel mulai membaca dan lalu bel tanda berhenti membaca–dan mengembalikan buku itu ke rak simpan dalam kelas, seakan tak ada kegiatan membaca yang rutin.
Karena itu–konsekuensinya, katanya–, apa nikmatnya membaca dalam 15 menitan, sebab nikmat membaca itu didapat dari (sampai) ada di titik lupa waktu dan lupa apa-apa karena suntuk membaca–terutama karena pukau itu buku fiksi. Lantas hal apa yang didapat dari hanya 15 menitan membaca, dan diulang 15 menit lagi keesokan harinya dan di keesokan harinya dan lagi? Apa itu tidak (malah) membuat siswa jadi trauma membaca, dan amat enggan untuk membaca lagi bila itu hanya berdurasi 15 menit? Lantas hal itu diperparah dengan kenyataan, bahwa orang tua dan guru, (relatif) selalu beranggapan, bahwa membaca itu harus membaca buku teks pelajaran dan bukan buku non-pelajaran, apa lagi hal percuma macam buku fiksi–dan itu diekspresikan dengan melakukan laku razia untuk merampas dan memusnahkan buku non-pelajaran, terlebih buat buku fiksi, roman percintaan dan seterusnya. Dan, di titik ini, kata Imaniar, bukankah itu akan membuat si siswa malas membaca dan para orang tua–bahkan guru–semakin antipati pada siswa yang haus membaca buku non-pelajaran?
Lantas apakah tidak pernah dipikirkan, adanya efek antipati macam itu dari usaha untuk menggalakkan upaya membina serta membiasakan membaca dan terutama bukan buku teks pelajaran?
***
SAYA pikir ada sebuah atmosfir, yang kurang dipahami, ketika gagasan menggalakkan membaca dan laku literasi itu dicanangkan. Yakni, fakta yang ditandai oleh Walter J. Ong, bahwa masyarakat itu terbagi atas dua. Yakni masyarakat kelisanan (orality) dan masyaraat keberaksaan (literacy)–satu state of mind yang bertentangan dan sangat berbeda. Pada masyarakat kelisanan, komunitas mendasarkan diri pada kebersamaan, keguyuban, serta menolak tumbuhnya (suatu) pribadi (unik)–hingga tanggung jawab diserahkan pada kelompok. Sedangkan pada masyarakat keberaksaraan, komunitas mendasarkan diri pada penumbuhan pribadi yang mandiri, memiliki sikap kritis, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil. Jadi cita-cita literasi itu, sesungguhnya, mendidik agar siswa mau bersaing secara kompetitif, dalam acuan individual, berlatih agar selalu bersikap kritis, serta berani mempertanggungjawabkan kekritisannya.
Dan itu–dalam acuan Timur–sangat tak disukai banyak pihak–bahkan para guru amat ringan untuk menganggap kalau siswa yang individual mandiri seperti itu sebagai si yang kurang ajar dan tak tahu etika sopan-santun. Dengan kata lain, masyarakat kita memang masih ada di taraf masyarakat kelisanan–meski berlangganan koran, dan tak heran kalau ia sangat suka berita gosip artis di TV, yang bersipat lisan pasif mempercaya, dan itu termasuk jenis the second orality, kelisanan yang lebih canggih.. Terlebih bagi masyarakat yang belum biasa baca, tak biasa membaca dan hanya pasif selalu diberi tahu. Dan karenanya, acuan membaca selama 15 menit per hari sebelum jam pelajaran dimulai itu terasa sangat berlebihan. Bahkan bisa merangsang perbedaan pendapat yang tajam di antara guru serta murid, padahal kita dibiasakan agar setiap pendapat guru itu diiyakan dan murid sepenuhnya orang yang tak tahu apa-apa dan belum tahu apa-apa hingga perlu diajari dan dididik agar jadi tahu. (Sesuai pemeo, ”Guru, ratu, wong atua …”, karenanya mereka marah kepada gadget dan internet, kemudahan teknologi yang membuat murid tahu lebih banyak dan lebih detil dari mereka yang ketinggalan zaman).
Mungkin potensi yang tidak terduga itu yang sedang dimanipulasi–bahkan usaha untuk merangsang kekritisan siswa dianggap hal yang membahayakan, sehingga sebelum mereka jadi mahasiswa, maka potensi kritis harus dikendalikan karena itu dianggap ihwal yang bisa membuat wibawa pemerintah dan Negara rusak (ingat kasus NKK di era Orba).
Dan itu yang membuat siswa hanya dilatih membaca setiap hari selama 15 menit, dengan buku yang telah diseleksi sekolah, meski atas nama moralitas, sebelum suntuk dengan pelajaran–bahkan, kini, itu hanya bermakna 15 menit di setiap lima hari, karena Sabtu dan Minggu libur, dengan belajar suntuk sampai jam 15.00 per hari, dengan tidak perlu terlalu banyak PR. Dengan kata lain–dengan idea full day school, kapan sebenarnya mereka bisa bebas dan leluasa membaca fiksi? Kapan mereka menyibukkan diri dengan buku yang sama sekali non-pelajaran?
***
PADA dasarnya, sebagian besar dari masyarakat kita itu masih masyarakat oralitas, Dan meski merasa bagian dari masyarakat yang membaca, tapi keberaksaraannya itu sangat pemilih, hingga menganggap (baca: beranggapan) bahwa bacaan fiksi dan sastra itu tidak berguna, hanya sebuah wishful tinking dibandingkan dengan teks pengetahuan. Dan kalau tidak menjadi si pemilih preferensial yang sangat subyektif begitu, mereka selalu beranggapan bahwa peranan seorang ahli itu vital, serta seharusnya diistimewakan di tengah masyarakat, dan itu adalah porsi (bagi) mereka, terutama di tengah masyaraat yang pasif tak pernah ingin tahu dan menjadi tahu akan apa-apa. Maka tidak aneh, kalau meski punya perputakaan pribadi–yang nilainya bisa lebih mahal dari peralatan dapur dan furnitur keluarga, hingga mereka amat banyak mengoleksi ensiklopedia dan buku teks, yang tak pernah dibaca–, maka mereka sangat suka ngerumpi, sangat suka bagosip, serta nya-nyap dalam ihwal hoax–sesuatu yang membuat mereka tampil dominan di tengah ibu-ibu kampung dan diakui sebagai yang paling tahu, padahal di masyarakat literasi setiap orang itu tahu banyak dan dihargai karena punya pendapat pribadi.
Kemandirian yang dihargai. Tak pernah mau punya pendapat seragam dan (terlebih) tunggal demi kebersamaan kelompok, yang malahan harus dijunjung tinggi, diutamakan–jadi tak heran kalau diksi berontak dan individual, yang dianggap hampir mbalelo saat ini adalah keberanian untuk memasang tag yang berbunyi, ”2019 ganti presiden–karena, seharusnya, justru ”sekali lagi, jabatan kedua”. Tapi benarkah begitu? Tapi kita ini bagian serta anggota kelompok masyarakat oralitas atau masyarakat literasi? Tapi apa memang kita sedang dilatih serta mendidik anak-anak untuk jadi generasi literasi yang biasa membaca, terbiasa menyimak realese tertulis, dan kritis mengapreasinya dan lalu menanggapinya secara tertulis–dan tidak si sekedar menyeletuk, bersuara serta pura-pura tak mengatakan apa saat didebat, atau ngotot berkata meski itu akan dibalas tuduhan telah menyebarkan isu kebencian dan memancing hoax, karenanya harus diluruskan cara berpikirnya oleh Polisi dan UU ITE? Begitu?
Absurd sekali!***
Beni Setia , pengarang