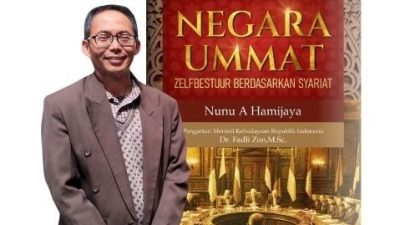“Dan kita tidak butuh kesepakatan, hanya butuh jalan pulang…” (Nandanggawe, 2022)
CARA kita menjelaskan “konstruksi” pada dasarnya merupakan konstruksi itu sendiri. Di sinilah paradoks dimulai kembali. Kita tak bisa bebas dari wawasan dunia, dan setiap wawasan selalu menjanjikan penjara kebenaran.
Paling tidak kita mengenal konsep “konstruksi linguistik”, bahwa apa pun yang kita anggap demikian halnya pada dasarnya merupakan bangun bahasawi, dan rumusan ini mengkonstruk kita dengan cara tersebut. “Tuhan” pun kini termasuk ke dalam teori konstruksi, karena Ia kita kenali melalui konstruk-konstruk bahasa agama, terutama bahasa para pemukanya yang dengan bebas atau akademik menafsir siapa Tuhan dan mesti bagaimana kita mencintai-Nya.
Tentu saja aneh jika kesadaran konstruksional merupakan kesadaran yang paradoks karena menjadi konstruk baru bagi para penggunanya, tapi dengan cara apa kita dapat melarikan diri dari paradoks macam itu? Jawaban untuk hal ini merupakan pertanyaan juga: jika tanpa bahasa dengan cara apa Tuhan dapat menampakkan dirinya kepada kita?
Mari kita periksa melalui analogi gender. Gender bukan kelamin, bukan tentang penis dan vagina, tapi bagaimana kenyataan biologis tersebut diteruskan dalam budaya: perempuan tak boleh main mobil-mobilan, dan laki-laki tak boleh main boneka. Laki-laki atau perempuan kemudian menjadi konstruk kultural: keharusan etis memaksa masing-masing untuk memenuhi moral maskulin dan feminin. Anomali di antara keduanya kemudian disebut bencong dan waria.
Setelah kita tahu teori konstruk budaya macam itu, apakah kita lantas membenarkan kenyataan gender sebagai produk budaya dan bukan produk biologi/alam? Sejauh kita percaya sejauh itu pula kita memerangkap diri dalam paradoks: katanya kebenaran itu konstruk, tapi mengapa kita memasuki konstruk baru, yakni konstruk budaya atau bahasa yang sebenarnya juga konstruk.
Iya, tidak?
Kalau sudah mengerti dengan paradoks tersebut kita juga akan mengerti mengapa Tuhan kini pun hadir dalam logika konstruk, tak lebih karena cara berpikir macam ini tidak pernah diperiksa ulang dan kita selalu mudah setuju bahkan latah dengan kebaruan wawasan dunia.
Paling tidak hal ini dapat segera dibuktikan dengan mudah saja: orang tanpa wawasan biologi bisa mengatakan bahwa gender bukan biologi tapi budaya! Bagaimana bisa lulusan kajian budaya dapat mengatakan hal itu jika ia tidak pernah belajar biologi?
Dalam satu kesempatan Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya adalah feminis dan ini adalah contoh pandangan orang yang sudah tercerahkan wawasan konstruksional, seolah-olah menjadi apa pun cukup dengan akal sehat dan tak perlu pengalaman tubuh. Lalu Gadis Arivia mengatakan perkatakan Rocky tersebut tidak mungkin dan hal ini merupakan contoh dari pandangan orang yang menolak konstruksi. Bagi Rocky laki-laki dapat merasakan perempuan (lupa bahwa merasakan tidak mungkin dengan wawasan gender atau feminisme atau akal sehat), dan bagi Gadis rasa itu tidak bisa diambil alih (bisakah laki-laki merasakan sakitnya melahirkan? Sakitnya datang bulan?). Maka, laki-laki tak pernah mungkin jadi feminis.
Lalu saya atau Anda harus berpihak kepada siapa? Rocky atau Gadis? Saya kira setiap keberpihakan merupakan awal mula kebenaran. Ketika saya setuju pendapat Gadis, saya memasuki kebenaran yang diberpihaki saya sendiri. Benar bahwa saya dapat menerima logika Gadis dan menolak logika Rocky, tapi menerima pada dasarnya mengantarkan saya pada keberpihakan.
Lihatlah apa yang kemudian terjadi, saya percaya dengan teori yang saya temukan: kebenaran adalah keberpihakan! Bahwa saya muslim, jangan-jangan saya berpihak kepada Ustad Abdul Somad dan bukan kepada Romo Muji karena beliau Katolik. Karena itu, saya melihat jangan-jangan mereka yang menghujat Arteria Dahlan beberapa waktu lalu adalah yang berpihak kepada Sunda dan yang menghujat Edy Mulyadi berpihak kepada Dayak dan yang menghujat Menag Yaqut Cholil berpihak kepada toa!
Ngomong-ngomong soal analogi toa dan anjing itu saya sendiri melihat fenomena yang seru, bahwa yang saling menggonggong bukan sekadar anjing tetapi kita semua, dan manusia memang makhluk yang bersahut-sahutan seperti toa karena selalu masing-masing merasa perlu memperbesar kebenaran. Kapan kebenaran disunyikan kalau bukan melalui jalan sunyi…
Pada satu kesempatan, perupa Nandanggawe menenangkan kepala saya yang berisik hingga rasanya melewati 140 desibel. Saya bilang kita ini menganut monisme ketuhanan (seperti jelas dalam sila pertama Pancasila), tapi rupanya kebenaran tidak pernah tunggal dan selalu milik manusia-manusia yang berpengeras suara, plural.
Nandang bilang “Biar saja, dan memang kita tidak butuh kesepakatan dalam kebenaran. Kita semua hanya butuh jalan pulang agar bisa bertemu Tuhan dalam diri-Nya.”
Saya terdiam, tetapi saya menambahkan dalam hati bahwa Tuhan ada dalam diri setiap orang, dan setiap orang mestinya bisa pulang setiap saat untuk memeriksa jalan pulangnya itu. Pulang ke dalam diri adalah pulang ke jalan-Nya. “Ana al Haq”, aku adalah Tuhan, mungkin sebuah konsep yang bisa dikonstruksi ulang untuk menyadari memang dalam urusan kebenaran kita sering merasa benar sendiri seakan-akan kita adalah Tuhan. Betapa sombongnya kita hingga mungkin tidak ada satu pun pandemi yang bisa membuat kita takut mati karena kita adalah kebenaran itu sendiri.
Nandang menambahkan kemudian bahwa hanya seni yang bisa membuat kita pulang ke jalan-jalan sunyi. Saya setuju, dalam seni tidak ada pengeras suaranya, kecuali seni kuda lumping di kampung saya sendiri yang sindennya, seorang lelaki gemulai, sambil bernyanyi sambil menggendong toa dan sekotak aki dan amplifier, dan ia seakan tak merasakan kebisingan sama sekali, orang-orang pun berjoged hingga kesurupan. Kebisingan kapan waktu memang mengasikkan juga.***
Arip Senjaya, dosen filsafat Untirta, alumni FPBS UPI dan Ilmu Filsafat UGM. Mengarang dan menerbitkan berbagai buku ajar, esai, cerpen, puisi, dan karya ilmiah, banyak sudah yang dimuat di dalam dan luar negeri. Buku terbarunya, 2021, adalah antologi puisi berbahasa Sunda Ceurik Arsénik. Email: aripsjy@untirta.ac.id