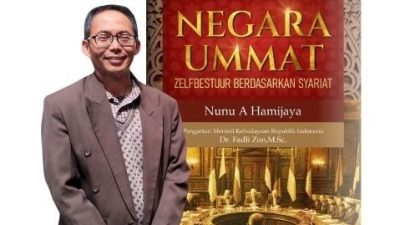SEBENARNYA semua puisi itu terikat oleh aturan, baik puisi kontemporer, apalagi puisi klasik. Yang membedakannya adalah jenis ikatan dan kelonggarannya, serta dalam menerapkan aturannya. Puisi klasik sangat erat dan ketat menggenggam aturan, sedang puisi kontemporer lebih longgar.
Kita bisa melihat ketatnya aturan yang digenggam dalam puisi klasik, misalnya pada haiku dari Jepang itu, yang hanya ada tiga larik, di mana larik pertama suku kata hanya 5, larik kedua ada 7, dan larik terakhir ada 5. Total jenderal suku kata dalam haiku ada 17. Selain itu, harus ada penanda waktu dan impresi dalam 17 suku kata itu, bagaimanapun caranya.
Bagi saya, puisi haiku itu selalu terasa relijius, sebab aturan-aturannya yang bersifat numerik, selalu mengingatkan pada angka yang ada dalam terminologi ajaran Islam. Misalnya suku kata yang harus 17, mengingatkan pada jumlah rakaat salat wajib yang berjumlah 17. Lalu suku kata 5 di larik pertama dan ketiga, seakan mengingatkan pada Rukun Islam serta jumlah solat wajib yang juga terdiri dari 5. Kemudian suku kata 7 pada larik kedua, adalah angka yang disukai Tuhan, sebab alam ini diciptakan selama tujuh hari, sehingga jumlah hari menjadi tujuh, bumi dan langit ada 7 lapis, bahkan benua dan samudra pun, bila dilelempeng mah ada 7.
Bila aturan dalam haiku dilanggar, akan menjadi haiku yang cacat. Puisi klasik khas Nusantara, yaitu pantun, juga menerapkan aturan yang cukup ketat, tapi sejujurnya, lebih longgar dari haiku. Makin ketat aturan, makin sulit itu puisi ditulis, dan bila para penulisnya makin tekuni, diam-diam tentu makin menambah kecerdasan. Bisa jadi orang Jepang lebih cerdas daripada orang Indonesia, karena haiku lebih kompleks dan sulit dibanding pantun, dan dengan sendirinya lebih memberikan tantangan untuk seseorang mengasah kecerdasannya.
Saya jadi terpikir dua hal. Pertama, etos kerja orang Jepang yang merumuskan haiku itu, bisa jadi lebih ulet dan tekun, tahan banting dan mrmiliki tenaga ‘endurance’, karena ikut dibina oleh semangat berhaiku, supaya tidak melahirkan haiku yang cacat. Melahirkan haiku yang cacat, bisa sama fatalnya dengan melahirkan mobil atau motor yang tidak sempurna. Karena itu, mobil dan motor harus disempurnakan, supaya tidak mencelakakan. Juga haiku harus disempurnakan, supaya etik dan estetik. Etik menurut aturan baku, dan estetik menurut pertimbangan kecerdasan. Maka bisa jadi, haiku bukan hanya melatih kecerdasan intelektual, namun juga melatih kecerdasan emosional, sekaligus spiritual.
Untuk hal ini, tolong anggota DPR mendanai saya, untuk wawancara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jepang. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, apakah haiku diajarkan di sekolah dan menjadi mata pelajaran yang wajib dikuasai?
Pikiran kedua, bahwa karena puisi klasik itu mengikat dan terikat, maka manusia perlu patuh dan taat aturan, supaya terdidik sejak dalam diri, agar tidak main terabas dan terobos.
Lalu lintas di negeri kita yang sering macet dan semrawut, mencerminkan bahwa kita masih suka main terabas dan terobos aturan. Pikiran lanjutan dari pikiran pertama ini, inginlah saya agar seluruh calon pejabat, dari mulai pejabat RT hingga Presiden, kepala sekolah hingga kepala dinas, manajer hingga redaktur, wajib bisa menulis puisi terikat. Tapi pikiran ini akan ditentang oleh orang-orang DPR dan DPRD, juga oleh pajabat dan aparat, karena dianggap membual dan kamalinaan.
Namun catatlah ini, bahwa di kesenyapan malam, ketika langit murung dan kelam, atau ketika meriah oleh gemintang, King David melantunkan pujian lewat Mazmur (Zabur). Musa menerima kata di Bukit Tursina, langsung dari Tuhan. Umat Islam meyakini, bahwa Tuhan pernah berkata langsung kepada manusia, hanya dengan Musa (wa kalimallahu musa-a taqlima). Bisa jadi dengan Adam pun, Tuhan bersabda melalui Jibril.
Lalu, dalam Quran amat jelas dan tegas terdapat Surat para Penyair, yaitu surat nomor 26. Sungguh tak ada Surat para Politikus dalam Quran.
Kemudian, kata pertama yang diwahyukan dalam Quran itu berbunyi: Iqro (bacalah, pahamilah, laksanakanlah kebaikan isi Quran ini). Jadi, bila usulan nihilistik saya ditolak, sebenarnya siapa yang membual nan kamalinaan? Yang membual adalah mereka yang beragama namun tidak menjalankan agama, oleh karena itulah mereka banyak melanggar aturan, semisal korupsi berjamaah!
Puisi terikat pola baru kini bermunculan, dari Sonian hingga Nainos, dari Pattidusa hingga Sadutipat, atau dari akrosmidanian hingga akrostik supir truck. Bagus itu, ya beneran bagus euy! Namun sebaiknya, jangan hanya sampai di situ, tapi harus pula beranjak ke puisi kontemporer yang lebih memberikan ruang kebebasan dan kemerdekaan.
Puisi kontemporer harus dipelajari dengan jiwa yang liar. Sebab dengan adanya kebebasan dan keliaran itu, terutama dalam kerangka akademis, pengetahuan jadi makin berkembang kan, Gan?
Kebebasan berpikir kerap melahirkan kecurigaan, pertanyaan, bahkan sanggahan terhadap sesuatu yang dianggap sudah baku, pakem, konvensi, teori, tesis, jumud. Pertanyaan melahirkan anti-teori, anti-tesis, sehingga lahir sintesis. Sintesis diteliti dan dirumuskan kembali, lahir tesis baru atau teori baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan.
Begitu dan begitu peradaban ini berkembang kan, Gan?
Tapi kebebasan dan ikatan mestinya memang dijalankan seiring, supaya pikiran mencar namun jiwa terdalam tetap mengakui bahwa bumi yang kita pijak ini, masih di bawah kuasa Satu Tuhan. Sebab puisi kontemporer yang bebas itupun, tetap masih berpijak pada ikatan. Adanya unsur musikalitas, yaitu pola ritma, ritma, metrum, serta adanya permajasan, juga keharusan menegaskan amanat, imajinasi, dan suasana, menunjukkan bahwa puisi kontemporer tetap berpijak pada aturan.
Jadi, sebebas-bebasnya berpikir dan bertindak, tetap harus dibuatkan aturannya. Aturan-aturan untuk berbuat bebas! Ah, sungguh kontradiktif.
Namun tidak sedikit pejabat dan aparat kita justru terbalik. Ari pikiran terikat sehingga sulit berkembang dan mengembangkan kurikulum misalnya, tapi jiwa malah bebas dan liar, sehingga wani korupsi pan?
Sekian dan terima kasih euy! ***
Doddi Ahmad Fauji, Penyair.