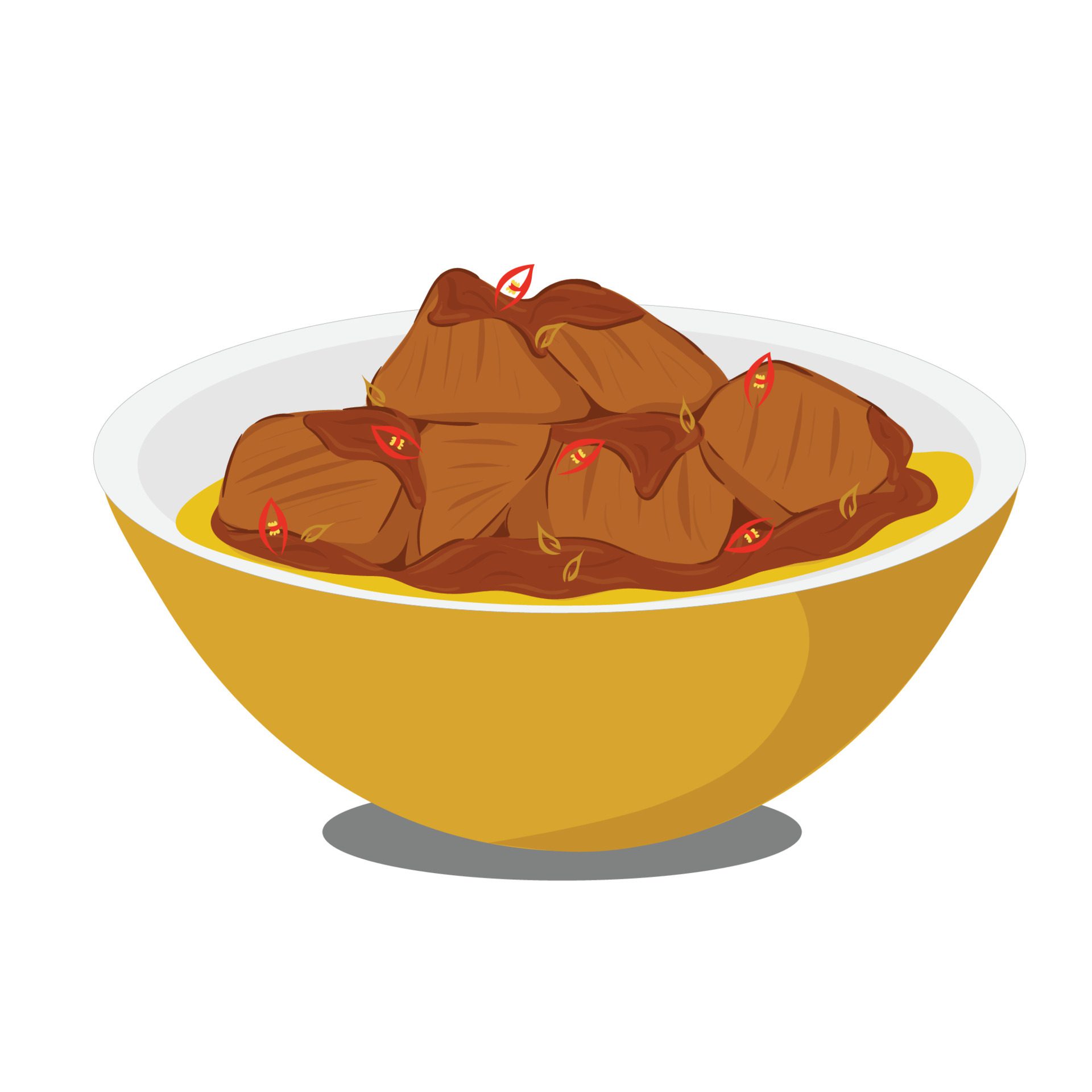SUARA selawat baru saja melintasi rumahku. Begitu nyaring puji-pujian itu dilantunkan anak-anak yang menabuh rebana sambil menyenandungkan kecintaan dan doa keselamatan pada Nabi Besar kita. Ya, kesemarakan amat terasa, sebab hari inilah hari terakhir dalam setahun mereka mesti berlapar-lapar, menahan dahaga dan nafsunya pada sesama, sebagai persiapan menuju hari kemenangan 1 Syawal besok, diawali salat Idulfitri di lapangan sebelah masjid.
Keluargaku baik-baik sekarang. Bagaimana keluargamu? Ah, Tin, entah kenapa, aku mesti selalu ingat pada tradisi keluargamu itu. Dulu, di meja makan rumahmu selalu dua keluarga kita berkumpul. Bapak, ibu, dan tiga adikku turut serta meramaikannya bersama bapak, ibu, dan dua adikmu. Tentu, tentu. Kau masih ingat, kan? Makanku selalu yang paling banyak, penuh selera, dan piringku selalu penuh isian. Ibumu paling senang melihat masakannya kusantap kelewat dokoh dan marem.
Tin, engkau tentu masih ingat ketupat rendang buatan ibumu. Hangat pulen nasi padat dalam ikatan simpul rumbia kelapa, dilumuri bumbu hitam kecoklatan dan pedas dari rendang yang dimasak berjam-jam oleh ibumu itu selalu memancing selera bahkan sebelum bapakku mengetuk pintu depan rumahmu.
Keluargamu begitu baik padaku, Tin. Lain dengan ibu atau bapakku. Sesudah aku menetap sekian lama di Singapura, barulah aku tahu, sikap Bapakku itu bukan hemat namanya, tetapi kedekut. Begitu hematnya dia, bahkan buat urusan makanan. Aneh, Bapakku tak pernah malu setiap kali datang membawa perut kosong dan mampir ke rumahmu, sekadar mengisi perut yang kami kosongkan sejak sebelum salat Ied mulai pukul setengah tujuh pagi.
Di kotaku ini, yang jaraknya tak kurang dua ratus kilometer dari kampung kita, aku sudah terlalu lama tidak merasakan rendang senikmat buatan ibumu. Ya, ya, tentu saja, aku takkan lupa, Tin. Keluargamu kini memusuhi rendang daging. Bukan, percayalah, itu bukan kesalahan kau atau aku. Itu ulah sejarah yang dulu mengubah jalannya dunia, dunia kita tepatnya. Sejarah menjauhkan aku dari rendang ibumu, juga dari bapak dan ibuku. Untuk yang pertama, mungkin dapat saja kubeli rendang di restoran lain yang rasanya teramat jauh di bawah rendang ibumu. Tetapi sampai sekarang, aku belum tahu toko mana yang menjual ibu sebawel ibuku atau bapak yang sepelit bapakku.
Kau dan aku masih sama-sama kecil saat peristiwa itu terjadi. Siapa yang sebenarnya tahu, manusia kurang ajar yang di malam itu merampas pedang dari tangan Tuhan dan dipakainya mencabut nyawa tujuh jenderal yang digelari “Pahlawan Revolusi” itu? Ya, kau bertanya, seperti aku juga bertanya. Di antara kita tak ada yang bisa menjawab soal. Kata Bu Guru, itu rahasia negara. Anak kecil jangan banyak tanya! Agar jadi anak yang berbakti bagi nusa bangsa, kita cukup beramai-ramai menudingkan jari sambil menyerapah mereka yang tak pernah memasuki pengadilan untuk dijatuhi hukuman.
Kata bapakmu, siapa salah itu tak penting. Satu yang jelas: jauhi aku sekeluarga. Kau lantas patuh saja pada perintah bapakmu. Persahabatan, keakraban, dan kedekatan kita begitu saja digunting putus waktu.
Aku tak pernah mengetahui apa yang dilakukan bapakku. Di tengah keluarganya, bapak tak pernah mengakui, apakah dia ikut-ikutan dalam barisan manusia yang malam itu bergerak dalam kegelapan, beraksi nista mencabut nyawa sesamanya, kukira itu jadi rahasia bapak yang akhirnya ia bawa ke keabadian.
Ya, Bapak tak pernah mengakui itu.
Aku jelas tak mendengar perintah bapakmu untuk menjauhkan anak sulungnya dariku itu. Bapakmu yang pendiam tak memberi kemungkinan untuk siapapun kecuali ia sendiri dan Tuhan untuk mengetahui apa yang ia pikir dan rasakan. Cukup dari gelagatmu, aku sudah cukup menerima berita penahbisan keluargaku sebagai musuh keluargamu sejak hari itu.
Hari-hari ketika itu memang tidak jelas. Kau pernah cerita di pantai, waktu kita bermain layangan terakhir kalinya, bapakmu pernah tidak pulang empat hari. Ia berurusan dan diajak tentara yang malam-malam menjemputnya. Kau bilang, kau takut sekali, sampai ibumu menggelar selamatan supaya bapakmu cepat pulang. Ah, bapakmu memang pantas untuk dikasihani. Cuma semalam sesudah selamatan digelar, bapakmu kembali.
Bapakku sama. Ia juga diajak bapak tentara yang tinggi berseragam, menaiki bak mobil besar dan berisik. Bedanya, bapakmu kembali setelah empat hari, sedang bapakku mengembalikan namanya saja untuk kupakai sampai sekarang, sesudah empat puluh tahun.
Sesudah hari-hari itu lewat, bapakmu mendadak takut daging. Lucu memang, orang yang takut pada daging. Tapi sejak itu, ibumu tak pernah lagi memasak rendang di hari Lebaran. Lebaran tahun itu, aku dan ibuku masih menyempatkan diri datang. Bapakmu menyambut di ambang pintu ikut menyalami aku dan ibuku mengucap minal aidin wal faizin, tapi dalam mata yang dingin sekaligus wajah sendu.
“Kali ini, lebaran tanpa rendang daging,” cerita ibumu. Akhirnya ibu dan aku cuma menyantap ketupat dengan kuah opor yang sudah dingin. Daging ayamnya habis disantap rekan-rekan bapakmu yang datang lebih dulu, menggasak dan meninggalkan kuah dan bawang goreng itu buat ibu dan aku. Ya, ya, jangan bilang aku tidak mengingat itu lagi, Tin! Apakah keluargamu atau keluargaku yang berubah, kurasa kau yang mengetahui jawabannya.
Siapa sangka, itulah lebaran terakhirku di rumahmu. Setahun sejak itu, ibu dan aku diajak tentara untuk pindah ke rumah baru berbentuk barak besar dan panjang. O, sungguh tidak enak. Kami keluar dari sana setiap pagi, dimaki-maki sepuasnya oleh bapak- bapak tentara berseragam hijau loreng, lalu masuk lagi dan menunggu datangnya kiriman dari sanak-semenda yang tidak kunjung sampai.
Barak besar itu tak perlu kau cari. Kekuasaan yang puas bermandi darah merasa tak lagi membutuhkannya. Di sana sekarang berdiri kantor pusat sebuah korporasi asing yang pernah kau pertuankan. Tapi, asal kau tahu, di atas sebidang tanah di seberang Kantor Walikota itu, masih dapat kau raba tapak kaki ibuku yang berdarah-darah setelah disuruh berjalan kaki di atas beling agar mengakui telah ikut dengan suaminya di malam kelabu, pas pergantian bulan itu.
Aku menghitung hari sejak kami tertangkap. Ibuku pelan-pelan jadi menua, kulitnya menjadi hitam dan keriput, sering terbatuk-batuk, dan terkadang mengeluarkan darah. Hawa dingin dari lantai barak yang kami tiduri telah membuat paru-parunya bermasalah dan menganugerahkan kepadanya umur yang tidak panjang sesudah kami ramai-ramai diusir dari barak itu.
Orang menamai barak itu, Kodim.
Tidak banyak yang dapat kuingat dari empat tahun penahanan itu. Ibu tak pernah mendengar apa dosa yang menjerumuskan dia. Pun ibu tak mengerti apakah sudah impas dosanya ketika ia menerima pembebasan. Tapi, dan ini dia yang kuingat terus, kau tak pernah datang menjengukku. Kau, Tin, yang mengaku jadi sahabatku yang sejati dan paling erat, yang berbunga-bunga meyakinkan hatiku bahwa selamanya engkau takkan sudi meninggalkanku sendirian, ternyata diserang pikun yang begitu cepat.
Aku masih bisa berbahagia, tentu. Bapakmu sekarat sewaktu ibuku dan aku dilepas. Kau datang padaku buat mengemis, menunaikan wasiat bapakmu yang minta supaya aku bersedia mengimami salat jenazahnya. Akupun kau ajak menyaksikan malaikat bermain catur dengan bapakmu. Dasar payah, bapakmu kalah. Ia diajak memasuki pintu alam keabadian. Waktu itulah semua yang tak pernah bapakmu bicarakan kuketahui.
Maklum saja, ia tak menyukai rendang. Ia membenci daging, sebab daging terakhir yang ia pegang ialah batang kepala bapakku yang dia jagal di kaki Jembatan Bacem. Darah bapakku ikut menghilir bersama derasnya arus Bengawan Solo yang membawanya ke keabadian. Bapakmu itu takut pada daging, sebab daging terakhir yang dipegangnya dan darah terakhir yang disaksikannya masih mewujud dalam daging dan darahku.
Tidak, tidak. Kau tak salah membaca surat ini, Tin. Surat ini datang kepadamu bukan sebagai perkawanan, tapi juga bukan rupa permusuhan. Surat ini kukirimkan kepadamu supaya engkau tidak lagi pikun. Jangan menyangka sudah terbit perdamaian di antara kita. Pengakuan bapakmu sebelum ajal itu hanya memberiku keterangan tentang dosa yang sudah ia lakukan pada bapakku. Pada jenazah yang kuimami salatnya itu masih terendus bau amis darah orang yang teramat dalam kucintai, kukagumi, kubanggakan.
Dan surat ini. Surat ini tak akan mungkin sampai ke tanganmu, juga takkan kau baca, kalau aku memilih batal mengirimkan dan menulisnya. Ingatanku terlalu pedih untuk menulis sebuah pengakuan pada sejarah kita berdua yang dicerai-beraikan sang waktu. Kepikunanmu itu, ku-yakini adalah caramu melupakan, meski darah penjagal bapakku tetaplah mengaliri pembuluhmu sampai kau mampus nanti.
Sudahlah, aku tak berniat menabur dendam di atas kertas. Terlalu pahit dan ia memang tidak akan tumbuh jadi apa-apa. Malam lebaran ini, aku hanya mengakhiri pikun yang kau derita dengan perdamaian antara kita. Besok pagi, sebagai Muslim, aku mesti menunaikan kewajibanku merayakan kemenangan, seperti juga engkau. Marilah, bersama-sama kita hapus keburukan bapak-bapak kita, bapakku dan bapakmu, dan menyerahkan mereka pada penghakiman Tuhan yang tidak pernah keliru meski tanpa jaksa, naik banding, atau kasasi.
Kalau kau mau, datanglah ke rumahku. Di sini selalu ada rendang daging yang kumasak dengan keikhlasan, tanpa dendam dan kebencian. Hanya sebutir cinta yang membumbuinya; cinta yang tak pernah padam karena ia sejati. ***
Chris Wibisana, pengarang, kontributor lepas, dan peneliti sejarah independen. Lahir di Jakarta, 2003 dan saat ini menetap di Tangerang Selatan, Banten. Peringkat IX Lomba Menulis Cerita Pendek Nasional VIII Tulis.me dan Juara III Lomba Menulis Cerita Pendek Nasional X Tulis.me.
Sumber: Tulis.me