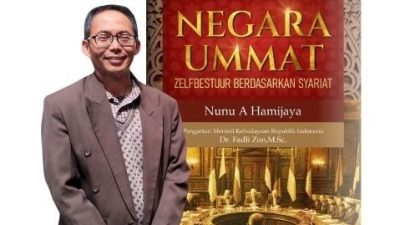Oleh Dadang A. Sapardan
DALAM beberapa kesempatan obrolan dengan beberapa teman dari berbagai profesi sering terlontar bahwa jadi kepala sekolah saat ini sangat didambakan oleh beberapa gelintir orang yang terjun dalam dunia pendidikan. Minimal terdapat dua hal yang diperoleh mereka dengan status kepala sekolah. Pertama, adanya peningkatan status dari guru menjadi kepala sekolah yang berbanding lurus dengan peningkatan citra diri di masyarakat sekitar. Kedua, peningkatan besaran penghasilan dalam status kepala sekolah karena menjadi pemegang anggaran yang masuk ke sekolah. Point kedua tersebut tidak sedikit mendapat cibiran dan kecurigaan dari beberapa pihak tersebut.
Melihat posisi kepala sekolah yang berperan sebagai manajer di sekolah, dasar pijakan yang digunakan adalah dua peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan—dahulu Menteri Pendidikan Nasional— yaitu: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Kedua regulasi tersebut yang menjadi dasar pijakan teknis terkait dengan eksistensi kepala sekolah.
Berdasarkan pada kedua regulasi tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala sekolah menjadi bundel portofolio yang begitu lengkap dan detail. Selain berbagai persyaratan yang sifatnya administratif, setiap calon kepala sekolah harus memiliki embrio kepemilikan kemampuan memanajemeni sekolah. Evident administratif atas adanya embrio kemampuan tersebut adalah keputusan yang menerangkan bahwa calon kepala sekolah pernah dan/atau sedang menjabat wakil kepala sekolah.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki, yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah memang memiliki perbedaan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru, seorang guru dituntut memiliki empat kompetensi yang lebih mengarah pada kemampuan dalam memanajemeni kegiatan pembelajaran semata, yaitu: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Membandingkan kompetensi kepala sekolah dengan guru, terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah tetapi kompetensi tersebut tidak harus dimiliki oleh guru, yaitu: manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Ketiga kompetensi tersebut bila ditelaah lebih dalam lebih mengarah pada tuntutan kemampuan setiap kepala sekolah untuk dapat memanajemeni sekolah, sehingga lembaga yang dipimpinnya mengalami perkembangan positif.
Akan halnya dengan dua kompetensi yang dituntut melekat pada guru tetapi tidak melekat pada posisi kepala sekolah, yaitu: pedagogik dan perofesional, keduanya bukan tidak dituntut dimiliki oleh seorang kepala sekolah, tetapi diasumsikan bahwa kedua kompetensi dimaksud sudah mengkristal pada diri kepala sekolah karena selama beberapa tahun ke belakang—selama menjadi guru—kedua kompetensi tersebut menjadi tuntutan mutlak yang harus dimiliki.
Dalam posisi sebagai pucuk pimpinan pada sekolah, tidak menutup kemungkinan lahirnya stigma—dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stigma dimaknai sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya—yang dilekatkan oleh segelintir orang. Stigma tersebut—terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan—bisa saja timbul karena kepala sekolah menjadi sosok sentral yang di antaranya berperan dalam memanajemeni keuangan sekolah. Posisi inilah yang tidak jarang mendapat cibiran sehingga melahirkan stigma yang terasa kurang mengenakkan.
Lahirnya stigma tersebut memang tidak bisa dipungkiri karena dibarengi dengan berbagai argumentasi yang mendekati kebenaran dan sulit terbantahkan—pada beberapa kasus atau beberapa kepala sekolah. Sekalipun demikian, stigma tersebut pada akhirnya digeneralisasi dan merambah pada sosok kepala sekolah lainnya yang memanajemeni sekolah dengan relatif baik–dibarengi kreativitas dan inovasi dalam pengelolaannya.
Adalah tugas para kepala sekolah dan pihak berkepentingan lainnya untuk dapat mematahkan berbagai argumen yang menjadi cikal bakal lahirnya stigma tersebut. Langkah yang harus dilakukan di antaranya memberi pembuktian bahwa argumentasi mereka merupakan alasan yang tidak berdasar kuat dan didasari atas asumsi semata. Upaya ke arah itu bisa dilakukan dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam memanajemeni sekolah.
Untuk dapat mengedepankan integritas dan akuntabilitas ini tidak hanya dapat dilakukan oleh segelintir kepala sekolah, tetapi harus dilakukan oleh seluruh kepala sekolah secara kolektif. Ketika masih ada sebagian kepala sekolah yang menganggap angin lalu akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam memanajemeni sekolah, tetap saja upaya untuk membangun citra dan mematahkan stigma dalam konteks kolektif akan sulit terbangun.
Langkah ke arah tersebut tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh kepala sekolah semata—dalam konteks perorangan dan komunitas—tetapi harus pula mendapat dukungan dari berbagai pihak eksternal, baik warga sekolah, maupun pemangku kepentingan lainnya di luar sekolah. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam upaya mengikis stigma yang selama ini dialamatkan kepada kepala sekolah. ***
Penulis adalah Kabid Kurikulum & Bahasa, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.